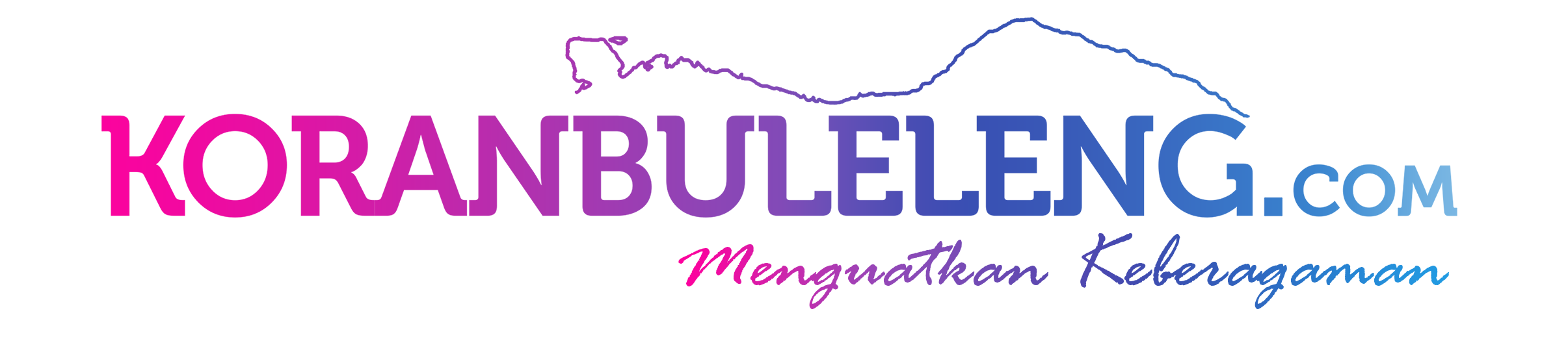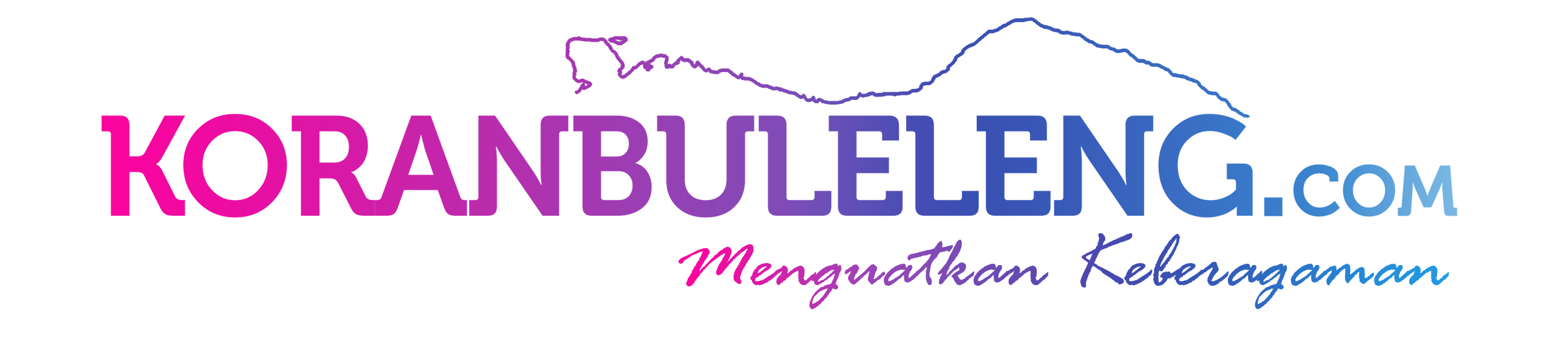Dr. I Wayan Artika, S.Pd., M.Hum. |FOTO : arsip koranbuleleng.com|
Esai ini dimulai dari sebuah desa di daerah Tabanan, tepatnya lagi di Kecamatan Pupuan. Desa ini persis berada di kaki Gunung Batukaru. Saking dekatnya, tekstur lereng gunung tampak sangat jelas, akar-akar pohon purba dan celah air ketika musim hujan.
Pendidikan di desa ini berawal tahun 1943 di SD tertua di Pupuan, kini menjadi SD Negeri 1 Batungsel. Sejak itu, usia pendidikan formal baru memasuki generasi kedua. Jadi sejarahnya masih terlalu pendek, apalagi dikaitkan dengan pendapat Confucius.

Guru-guru SD yang bertugas di desa ini didatangkan dari luar desa (Nyuling, Jegu, Penebel, dll.). Mereka tinggal di rumah semipermanen yang dibangun secara swadaya di tanah kalangan tajen dekat areal sekolah yang juga bukan tanah pemerintah. Hal ini membuktikan warga desa menyambut dengan suka cita dan harapan tinggi.
Kerja pendidikan dan pengajaran para guru di SD 1 Batungsel mampu menciptakan tujuan atau visi hidup baru di kalangan masyarakat petani. Mereka ingin anak-anaknya bersekolah lanjutan setelah tamat SD. Visi ini dijalankan dengan gerakan sosial masif untuk berlomba menyekolahkan anak ke kota karena sekolah lanjutan (menengah) belum ada.
Hasil panen kopi dan vanili atau ternak sapi digunakan untuk biaya sekolah. Dekade 80-an menjadi masa keemasan gerakan pendidikan petani kopi di daerah Pupuan. Anak-anak remaja desa yang sedang tumbuh meninggalkan desa mereka ke kota (Tabanan, Denpasar, dan beberapa orang di Singaraja). Sehari-hari biasa terasa desa sepi. Hanya para orang tua yang giat kerja untuk panen melimpah yang disiapkan bagi biaya pendidikan. Saking populernya gerakan pendidikan ini, di desa-desa lantas muncul istilah “pelajar” untuk menyebut anak anak desa yang bersekolah di kota.
Kejayaan kopi dan vanili dekade 80-an membikin anak-anak petani dari daerah Pupuan tampil jemawa di kota. Ketika itu, pembangunan infrastruktur industri pariwisata di Bali baru dimulai, yang kelak akan menggeser ekonomi pertanian, sekalipun akan meruntuhkan ekonomi perkebunan.

Kejayaan kopi dan vanili telah banyak mengantar anak-anak petani memasuki gerbang universitas terbaik di Bali (Denpasar dan Singaraja), Surabaya, Jakarta, Malang, dan Yogyakarta. Pada masa itu, pamor jurusan pariwisata masih kalah gengsi dengan teknik sipil, arsitektur, dan ekonomi.
Dari segi pemilihan fakultas, di kalangan mahasiswa dari daerah Pupuan, FKIP adalah fakultas kelas bawah. Hanya anak-anak petani yang lebih miskin memilih FKIP.
Demikianlah, seorang anak petani dari Batungsel, secara tidak sengaja masuk FKIP UNUD di Singaraja, yang semula dikira Fakultas Sastra. Ia tidak cermat membedakan nama jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah dengan Jurusan Sastra Indonesia. Setelah mahasiswa-baru diterima di lapangan Kampus Sudirman, ia pun menuju sebuah kota yang baru akan dikenalnya: Singaraja.
Ia hanya bermodal semangat kerja ayahnya, seorang petani kopi dengan satu akit sapi bali. Tidak penting baginya memikirkan mau jadi apa nanti setelah tamat. Bahkan, saking tidak pahamnya, ia juga tidak tahu jika FKIP UNUD adalah fakultas mencetak tenaga guru sekolah menengah.
Semangat belajar anak petani kopi yang ditempa hujan, angin, sambaran petir, tajamnya duri tuwung alasan, dan sayong Batukaru, kelak akan mematangkan pribadinya di Kampus Seribu Jendela, di sebuah kota tua, kota kolonial, berarsitektur peninggalan Belanda, pernah menjadi ibu kota Provinsi Sunda Kecil.
Di kelas-kelas bekas gedung sumbangan atau hibah Kantor Keungan, ia menyimak kuliah-kuliah para dosen berbagai gaya yang amat dikaguminya. Ia benar-benar menempatkan diri sebagai objek dengan kesadaran tinggi penuh penghargaan dan penghormatan kepada para dosennya, sebagaimana selalu disarnakan oleh bapak dan ibunya setiap kali pulang ke desa.
Di samping belajar dari para dosen, ia menghabiskan seluruh sisa waktunya untuk berkegiatan ekstrakulikuler. Bermain teater, mendaki gunung, berdiskusi, baca buku, belajar menulis, adalah kegiatan ekstra yang membentuk dirinya secara mandiri. Cita-cita terbesarnya, bukan jadi PNS, tetapi menjadi penulis atau kaum intelektual yang hidup di desa. Ia dan sejumlah kawan seidealisme, belajar keras menulis dan juga membaca buku-buku kritis, untuk menetralisasi hegemoni diktat kuliah yang kaku; agar mampu menembus barikade dan keangkuhan para redaktur media print capitalism. Walaupun perjuangan ini tidak sukses benar, dalam artian tidak juga selalu berhasil menembus barikade itu, namun semangat tetap menulis dan membaca tiada padam dan kini mengantar sekawanan mahasiswa yang juga bergaul dalam iklim multikultur kampus, menjadi wartawan, redaktur, editor, guru penulis, pengarang, menggerakkan kegiatan literasi, menerbitkan buku, dan lain-lain.
Ia dan kawan-kawan tamat dengan menyandang gelar sarjana pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh FKIP UNUD. Selanjutnya Singaraja mulai saat itu memiliki STKIP Negeri Singaraja (selanjutnya menjadi IKIP Negeri dan kini Universitas Pendidikan Ganesha). Sejarah pendidikan tinggi di kota ini memulai babak baru yang pada tahap-tahap selanjutkan, kota ini semakin populer berkat dinamika sebuah universitas yang embrionya bermula pada dua kursus (B1: Bahasa Indonesia, Perniagaan) pada 1955.
Ia memang tidak menjadi petani kopi dengan gelar S.Pd. Forum-forum pemikiran kritis selama kuliah, bagaimana ia dan kawan-kawan terobsesi dan memaknai gerakan mahasiswa di seluruh dunia, termasuk Soe Hok Gie (UI), dengan berbagai peristiwa penting yang melibatkan mahasiswa di berbagai Negara, seperti Peristiwa Lapangan Tiananmen, perjuangan Che di Cuba, Malari, NKK dan BKK; membangun idealisme baru baginya. Ia ingin kembali ke desa menjadi petani.
Sontak orang tuanya marah dan naik pitam. Merasa rugi menyekolahkan tinggi-tinggi. Untuk apa sekolah tinggi jika kembali ke desa hanya bertani. Apa kata orang desa. Bagi orang tuanya, itu semua adalah pilihan yang memalukan di masyarakat. Ia mengalami konflik idealisme dengan orang tuanya sendiri, petani kopi yang membangun harapannya agar tidak lagi menjadi petani demi kehidupan yang lebih baik (?).
Dengan bekal SK biasiswa Tunjangan Ikatan Dinas, ia kembali ke alma maternya, menjadi dosen. Hari-hari awal membuat dirinya amat kikuk. Kini ia ada di ruang dosen-dosen yang amat dia takuti dan hormati. Namun keteladanan karakter yang diberikan oleh alma maternya, ia mulai beradaptasi.
Jika kembali kepada sejarah pendidikan di Desa Batungsel, sebagaimana diceritakan pada awal esai ini, para guru di desa itu telah sukses tidak hanya sekadar membuka jendela ke masa depan tetapi melemparkan jauh ke lingkungan kehidupan baru seorang anak petani.
Di kampus Universitas Pendidikan Ganesha ini, ia menjadi skrup kecil pembangunan pendidikan di Indonesia. Pekerjaannya kini memang jauh dengan kehidupan orang tuanya namun inilah yang menjadi impian para petani kopi di Kecamatan Pupuan. (*)
Penulis : Dr. I Wayan Artika, S.Pd., M.Hum. (Dosen Undiksha, Pegiat Gerakan Literasi Akar Rumput pada Komunitas Desa Belajar Bali)