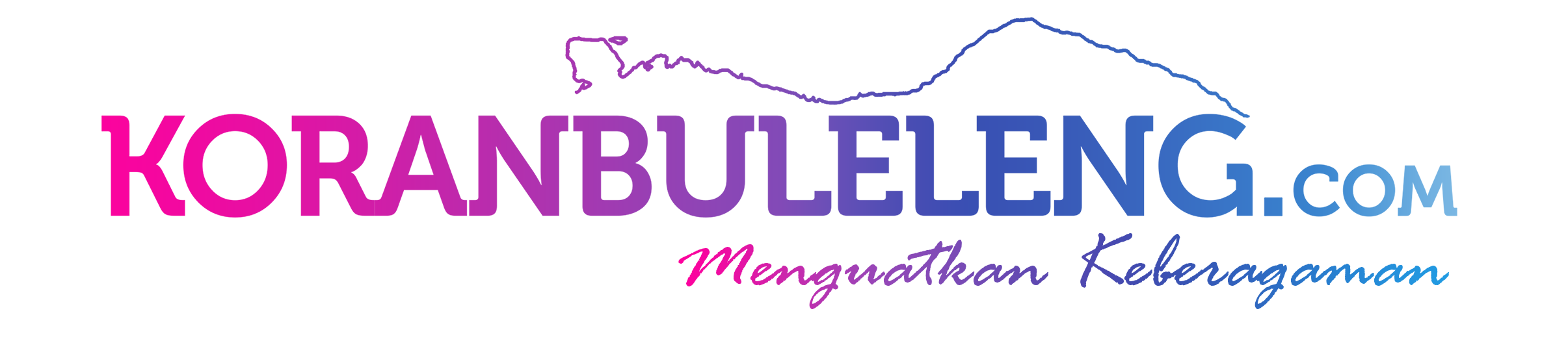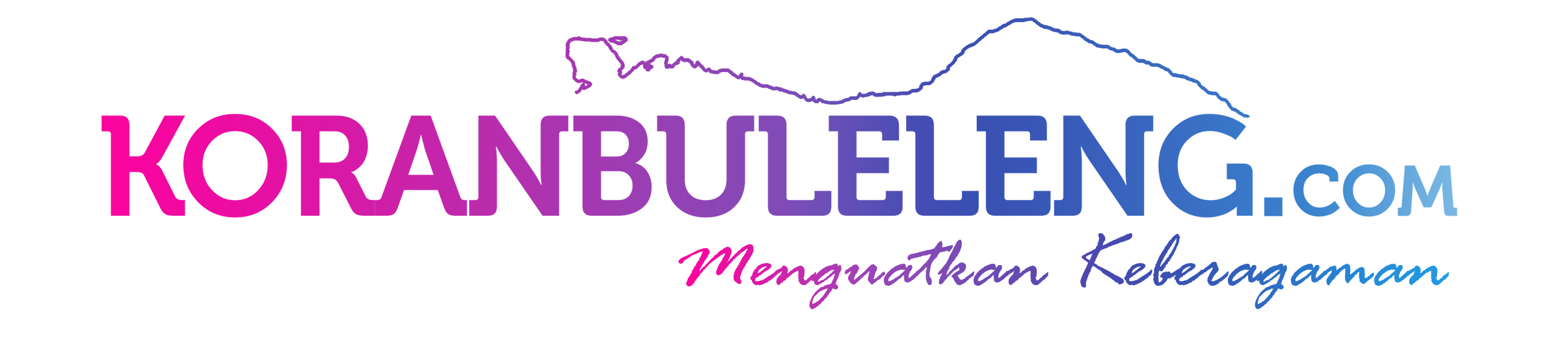“The Last Supper”, Perjamuan terakhir Umbu Landu Paranggi kepada I Made Astika (16 Maret 2021). Secara tiba-tiba Umbu hadir di rumah I Made Astika, di Desa Sebetan, Karangasem. Pada kesempatan itu, Umbu membawa tiga bingkisan untuk -yang Beliau sebut- TigaA: Artawan, Artika, dan Astika.|FOTO : I Made Astika|
Kontributor : Dr. I Wayan Artika, S.Pd., M.Hum

Dari buku yang berjudul Metiyem (2019) dapat dibaca kiprah Umbu Landu Paranggi, yang oleh Penyair Ketut Suwidja dalam puisi “Umbu Landu Paranggi” (1988) disebut “buronan kampung halaman”; di sebuah lingkaran studi Persada Studi Klub (PSK) Yogyakarta. Dia adalah bangsawan Sumba. Tulisan-tulisan dalam Metiyem bermuara pada pendidikan susastra yang dijalankan Umbu. Hal inilah yang dialami oleh para muridnya sehingga sebutan guru atau guru batin (Warih menyebut demikian) sangat melekat.
Umbu melakukan dua hal: berkarya sebagai penyair dan mendidik calon-calon sastrawan di lingkungan seputar ia tinggal (pada mulanya di Yogyakarta). Kelak, sejarah sastra Indonesia mencatat, Umbu dihormati dan dimuliakan sebagai guru. Hal inilah yang membedakan Umbu dengan sastrawan lainnya di dunia, yang dikenal karena salah satu karyanya; tapi Umbu dikenang sebagai laku guru sejati sastra, guru yang berkelana mengunjungi murid-muridnya, seperti dua minggu lalu, pada hari-hari akhir hidupnya, Umbu tiba-tiba hadir di rumah I Made Astika, di Desa Sibetan, Karangasem (16 Maret 2021 adalah kunjungan terakhir seorang guru sastra sejati kepada murid kesayangannya), dengan masih sempat membawa bingkisan untuk Gede Artawan dan I Wayan Artika.
Ia bukan guru dalam pengertian para mahakawi, yang asik bertapa dalam dirinya di tengah sunia hutan-hutan Jawa, yang bersekongkol menjadi purohita raja demi harta dan tanah, seperti para pujangga Jawa Kuna, dan mengubah adikarya kakawin untuk memuja sang raja di dalam kolofon, dan bahkan harus menyandingkannya dengan dewa tertinggi dalam sistem kultus agama dan raja.
Umbu bukan guru rahib bersemayam di dalam keharuman semi hutan yang hendak menjadikan dirinya semesta atau bahkan pusat melewati praktik-praktik meditasi seorang diri. Karena itu, Umbu telah menampik pandangan A. Teeuw bahwa sastra adalah jalan sunyi dan seperti pandangan Gao Xinjiang (penyair Cina) bahwa menulis adalah untuk diri sendiri. Bagi Umbu, tidak, sastra sama sekali bukan perjalanan sunyi seorang diri!

Jika harus disandingkan dengan H.B. Jassin, yang diberi gelar Paus Sastra Indonesia, Umbu menerima “ketidakadilan” dalam kerangka kritik sastra. Umbu sama sekali kurang disebut atau diakui oleh lembaga-lembaga kritik sastra. Wibawa atau kharisma Umbu sangat kuat dalam komunitas yang dibentuk/dibangun/dirintisnya. H.B. Jassin, benar-benar Paus Sastra yang bercokol di “biara gereja” yang suci, kritikus yang hanya bersentuhan dengan teks yang datang ke meja kerjanya. Tapi Umbu kritikus yang melahirkan sastrawan, seperti dokter kandungan dan kebidanan spesialis bayi tabung. Umbu mengenal habitat “rahim” atau ekosistem calon sastrawan. Umbu kontak secara holistik dengan embrio-embrio sastrawan, untuk disiapkan di cawan pateri menjadi janin di dalam rahim. Umbu secara tekun membantu mereka berproses, sejak sel telor disiapkan di ovarium hingga siap tetas dalam rahim. Jadi, teks atau karya yang dihasilkan hanya konsekuensi dari pendidikan sastra yang dikembangkan sebagi laku seorang sastrawan. Sebagai kritikus sastra, Umbu sedikit berurusan dengan teks/karya hanya salah satu aspek dari proses kreatif kerja seorang kritikus sastra.
Cara kerja Umbu dari perspektif kritikus sastra adalah penolakan terhadap pengertian kritikus ala Barat. Kritikus hanya berurusan dengan buku sastra, bentuk fisik karya, lalu memberi penilaian dan penghakiman. Kritikus Barat (yang strukturalis dan otonom) tidak mau tahu proses kreatif dan kehidupan seseorang dalam berkarya. Kritikus Barat hanya bekerja untuk teks/karya. Tapi Umbu mengambil peran lebih jauh, sebelum karya itu lahir dan ada. Umbu “melahirkan” dan kerja kritikus adalah proses panjang berkelanjutan di luar teks; dalam laku hidup nyata seorang calon sastrawan.
Untuk misi sastranya itu, entah sebagai kritikus, guru, atau apapun itu, Umbu membutuhkan infrastruktur teknologi yang paling dekat dengan sastra: media dan mesinnya. Teknologi sastra adalah teknologi yang berhubungan dengan percetakan, dokumentasi, dan distribusi atau penerbitan. Maka Umbu “menyusup” atau menjadi serumpun anggrek bulan di sebuah perusahan media atau koran. Pola ini dilakukan baik di Yogyakarta dan di Bali. “Pohon inang” yang ditempeli Umbu indah dan semarak dan dari suatu perspektif yang lebih khusus, kesenian, justru keindahan atau keharuman Umbu selaku anggrek bulan-lah yang lebih terlihat. “Pohon inang” yang menjadi tempat Umbu hidup diperlukan untuk melayani sastra dalam hal percetakan, penerbitan, dan publikasi (distribusi yang berke;anjutan). Walau sastra adalah dialog pada diri sendiri, sebagaimana ungkapan Gao dari Cina, namun guna sosial karya yang sehebat apapun baru terasa setelah dibaca oleh khalayak yang luas dan hal ini membutuhkan teknologi baca yang sejak era Gintenberg (penemu mesin cetak, leluhurnya kapitalisme cetak). Teknologi membaca itu adalah teknologi cetak-kertas dan distribusi salinan keras (hard copy); maka pada era 4.0 teknologi itu adalah digital-daring.
Media sangat penting bagi sastra. Kerja Umbu tak ada artinya jika tanpa teknologi media. Karena teknologi menguasai hidup manusia, demikian pula teknologi cetak dalam era panjang juga menguasai kehidupan dan sejarah, maka peran lain teknologi sastra akan disediakan, terkait dengan ketergantungan massa terhadap teknologi atau dalam hal ini media, yakni legitimasi sosial atau pengakuan, sejenis pembaptisa/pengesahan seseorang telah memilih jalan kritis, di “aula gereja”. Umbu bekerja lebih jauh lagi, proses seseorang berkarya sampai karya-karyanya layak diberi label Sastra. Bagi Umbu proses itu yang lebih realistis ketimbang kerja kritikus di dekat altar ketika membaptis seseorang jadi sastrawan. Bahkan Umbu tak perlu membaptis karena buah pendidikan sejati sastranya nanti akan dibaptis oleh para paus sastra dalam gereja kehidupan yang sebenarnya.
Betapa pentingnya teknologi media bagi kesusastraan dan keniscayaan ini memaksa Pramoedya Ananta Toer tak cukup melisankan Tetralogi Buru di hadapan para tapol 65. Ia membutuhkan teknologi tulis (kertas, pita, dan mesin tik) sebagai teknologi penyimpan novel Buru secara fisik berupa cetakan huruf-huruf dalam sejilidan kertas. Sampai di sini perjalan sastra belum selesai. Pram harus menyelundupkan karya ini ke luar Gulag Pulau Buru. Cara/tahap inilah yang memungkinkan publik menikmati kehidupan Minke, Annelis, atau Nyai Ontosoroh. Karena itu apa yang disampaikan oleh Gao bahwa ia menulis untuk dirinya seorang diri adalah pernyataan yang terlalu naïf. Sastra secara kodrati tidak selesai pada diri seorang sastrawan. Ini hanya perjalanan awal, ibarat tukik-tukik baru saja menetas dan bersiap di pantai mengarungi laut lepas.
Umbu amat menyadari hal ini. Untuknya ia lantas mencari koran sebagai teknologi komunikasi dan publikasi sastra. Maka koran yang dipilih Umbu bisa dikatakan sebagai “sekolah” atau “kampus” tempat Umbu meracik kurikulum, merekrut mahasiswa atau murid, menyelenggarakan proses “kuliah” sampai mereka diwisuda menjadi sastrawan Indonesia. Perilaku sekolah sastra model Umbu sebagai kritik kepada lembaga universitas sastra yang jarang melahirkan sastrawan. Mungkin karena inilah, nomenklatur fakultas sastra berubah menjadi fakultas ilmu budaya.
Cara kerja Umbu sebagai sastrawan, tidak mementingkan dirinya. Ia tidak mengejar popularitas jagat sastra. Tidak mengejar popularitas seorang diri yang buku-bukunya dijadikan komoditas kapitalis percetakan, distribusi, toko buku mayor/besar. Umbu melakoni jalan pendidikan sastra. Hal ini melahirkan banyak sastrawan dan jika Umbu memilih gaya Amir Hamzah atau Ahmad Tohari, maka dunia sastra hanya akan punya mereka berdua. Umbu memang telah memilih jalan “KB” sebagai penyair, seperti dialog I Made Astika dengan Umbu, di tengah pandemi pada 16 Maret 2021, tiba-tiba Umbu ada di rumahnya di Desa Sibetan Karangasem. Tapi “rahim” Umbu tetap subur mengandung dan melahirkan sastrawan. (*)