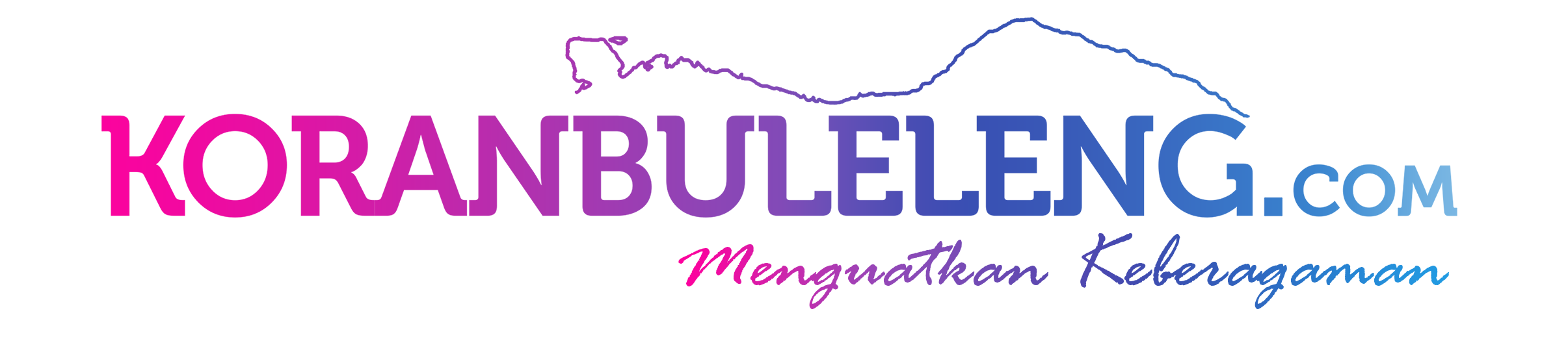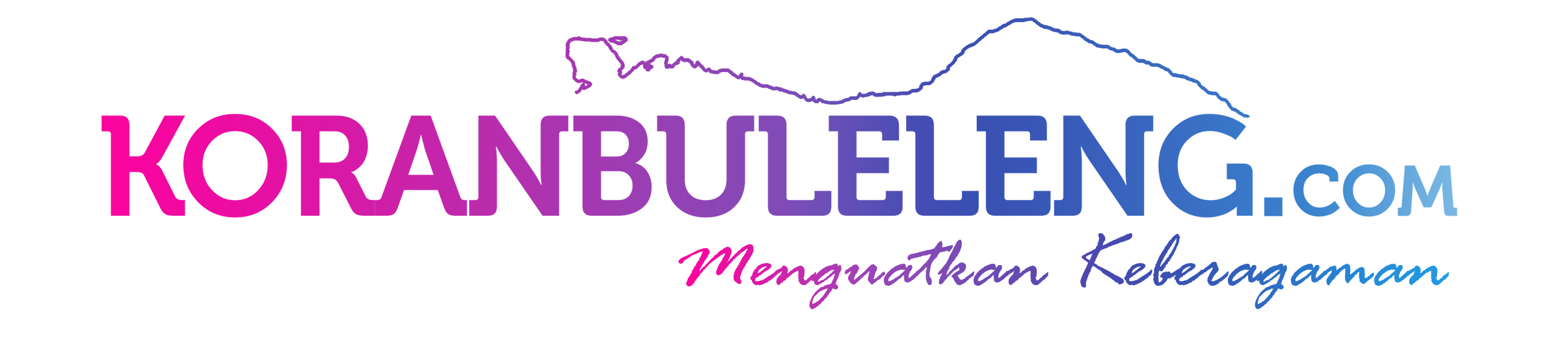Ekosistem air desa-desa Bali di masa lalu adalah sumber protein yang berkelanjutan; seperti laut, muara, rawa, sawah, sungai, telabah, pangkung, dan inrastruktur air terbesar di kawah-kawah purba gunung api hulu pulai: gugusan danau. Di habitat air ini, berbagai ikan, siput, kepiting, udang berbiak. Di sanalah rantai makanan bekerja dan tentu saja manusia numpang di dalamnya.
Manusia seperti elang, serangga, atau reptilia, ikut-ikutan jadi predator. Udang, berbagai siput, kepiting, aneka ikan tawar, payau, atau laut; jadi santapannya. Mereka kecanduan cita rasa aneka jenis ikan dan udang yang teramat lezat. Lantas mereka merumuskan akal yang mencipta suatu teknologi untuk memangsa. Teknologi menangkap ikan, udang, dan kepiting ditemukan, seperti pancing dan perangkap. Semua peralatan ini sangat ramah lingkungan dan tidak pernah menjadi ancaman kepada ikan, udang, kepiting, dan air. Kelak, titik baliknya terjadi ketika potas dan setrum digunakan untuk menghancurkan ekosistem air dan meracuni diri manusia sendiri. Pernah populer dan legal di desa-desa. Namun desa adat di Bali sadar dan telah membentengi ketat ekosistem desa mereka. Di mana-mana desa adat di Bali menerapkan larangan ketat: berburu, mempikat, nyetrum dan motas. Hal ini terbukti sukses meningkatkan aneka jenis dan jumlah pupulasi burung, seperti di Desa Kelating (Kerambitan, Tabanan).

Di samping teknologi dan seni pancing; dalam rangka menjalankan fungsi predator itu, masyarakat kuno di berbagai perdesaan Bali, telah menciptakan aneka jenis bubu dan dungki. “Ada berbagai jenis bubu, seperti bubu udang, testes, bubu lindung, dan bronjong, bubu ukuran bsar. “ Kata Putu Sinar, seorang ibu rumah tangga asal Desa Tangun Titi (Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan).
Perempuan ini membangun warung kecil tepat di pinggir jalan nasional Denpasar Gilimanuk, di Desa Bajra. “Saya sangat menyukai peralatan bubu.” katanya.
Ia berkeinginan membuka toko yang secara khusus menjual aneka jenis bubu dan dungki. “Toko saya ini sudah berjalan lebih dari dua puluh tahun.” katanya kepada Koran Buleleng 29 Juli 2022.
Namun demikian, satu per satu perajin bubu dan dungki di Desa Tanggun Titi meninggal. “Mangkin nak kari siki Pak, dan nike sampun lingsir.” kata Putu Sinar melanjutkan tuturnya dengan berbahasa Bali.








Ia menyambung dan rupanya sangat khawatir, apabila para perajin ulatan bubu dan dungki tersebut sudah tiada. “Benjang yan sampun ten mekarya, dije men tiang ngalih bubu sareng dungki nggih?” keluhnya.
Lewat toko kecilnya ini Putu Sinar telah membuktikan jika bubu dan dungki tradisional yang berbahan bambu, ternyata masih dibutuhkan.
“Mangkin nak anggen pajangan nike Pak.” Katanya. Ini adalah peluang namun tidak serta merta memberi keuntungan baik ekonomi maupun kebudayaan. “Nak ten nyak mangkin mekarye bubu sareng dungki Pak,” lanjutnya.
Menurut Putu Sinar, beberapa warga di desanya tidak mau lagi membuat bubu atau dungki karena merupakan pekerjaan yang sangat rumit dan memakan waktu lama.
Demikian pendapat Putu Sinar dengan harapan dan sekaligus kekhawatiran menggenangi wajahnya. Ia yang sangat mencintai ulat-ulatan tradisional Bali, telah berhasil mengenalkan bubu, dungki, kelabang atau kelangsah kepada khalayak modern, lewat toko kecilnya.

Kecintaan dan kekaguman orang-orang yang lewat, yang datang dari peradaban yang jauh dan sama sekali tidak mengenal ekosistem air dan teknologi menangkap ikan, udang, siput, dan kepiting; mengagumi keunikan bentuk aneka jenis bubu, bronjong, dan dungki yang terpajang di tokonya. Mereka biasanya mampir dan bikin foto; serta menyimak kisah dan kecintaannya kepada teknologi berbahan bambu ini. Dengan fasih dan penuh penghayatan, Putu Sinar biasanya bercerita. Ia tidak peli dan membiarkan para tamu yang mampir memotret. Mungkin saja desainnya dicuri dan dikembangkan di tempat lain. Demikianlah kepolosan dari masa silam yang sangat murah kepada ilmu. Laku saja bubu atau dungkinya, adalah kebahagiaan luar biasa bagi Putu Sinar.
Lewat cerita dan warung bubu dan dungkinya, Putu Sinar seperti tengah menyaksikan masa silam yang akan berhenti dan beralih ke masa kini. Ketika ekosistem air rusak, seperti plastik, diterjen, oli bekas yang mencemari sungai, telabah, pangkung, muara, hingga tepian pantai di Samudera Hindia, di dekat Desa Tanggun Titi; pastilah perkembangbiakan aneka jenis ikan, udang, siput, atau kepiting terancam. Lantas desa-desa dibanjiri produk food industry, seperti ayam potong atau lele tinja manusia; jelas akan mengubah jalanannya sebuah teknologi. Maka, teknologi perangkap ikan yang sangat ramah lingkungan ini pun tidak lagi ditekuni. Sudah tidak ada ikan. Apalagi yang bisa ditangkap? Lantas peralatan tidak perlu diciptakan lagi. Maka demikianlah, cara-cara sebuah item peradaban mati karena digusur dan ditinggalkan.
Namun ideologi postmodern sering kali bersikap kontras dan kontradiktif, menciptakan ruang-ruang baru, modern, dan ekslusif, bagi produk-produk teknologi dari masa silam. Terjadi peralihan fungsi yang hebat, dari alat menangkap ikan untuk kebutuhan praktis sehari-hari: mendapatkan protein hewani dari ekosistem air; kini menjadi hiasan ruang-ruang modern, seperti hotel berbintang, rumah mewah, atau villa.
Keadaan ini adalah peluang usaha yang sejatinya sangat menjanjikan. Namun demikian, maestronya sudah hampir habis dan tinggal satu atau dua orang, seperti kisah sedih dua orang penekun teknologi gerabah purba di Desa Pejaten (Wayan Budi dan Ibu Dana, laporan Koran Buleleng sebelumnya). Para pemilik modal bisa mengembangkan usaha di sektor ini. Hal ini memang sudah sering terjadi namun adalah menjadi praktik pencurian yang merupakan kejahatan kebudayaan. Semua desain dicuri dan dikonstrksi ulang dari barang-barang yang masih tersisa. Lalu dibuatkan pelatihan. Dicarikan tenaga kerja bayaran. Dari sisni sistem produksi menjadi mekanik untuk menghasilkan barang dalam jumlah besar. Lalu dijual dengan harga yang sangat mahal. Demikian pun yang terjadi pada produksi baru Patung Labirin di Desa Busungbiu (Buleleng, laporan Koran Buleleng tahun-tahun sebelumnya).
Bahkan produksi tidak lagi di desa asal. Pemilik modal bisa berproduksi di mana saja. Untuk menyadari kejahatan kebudayaan, maka kearifan produksi modern yang basisnya pada modal dan target memenuhi pasar, harus kiranya membayar hak cipa kepada desa-desa yang terbukti pernah menjadi pusat pengembangan teknologinya, seperti para perajin bubu dan dungki, yang masih ada di Desa Tanggun Titi. Atau, mengembalikan kebanggaan masyarakat setempat dengan membangun bengkel modern yang memilih lokasi di Desa Tanggun Titi. Orang –orang desa diberdayakan dengan memberi pelatihan cara menganyam dungki, bubu, bronjong, dan kelabang. Mereka tetap mewarisi nilai-nilai dan keterampilan dari masa silam dan dapat merasakan keuntungan ekonomi di masa kini; ketika bronjong, bubu, dan dungki tidak lagi berfungsi untuk menangkap aneka jenis ikan, udang, dan lindung karena pada satu sisi ekosistem air telah rusak; tidak lagi memberi berkah hidup kepada desa-desa di sekitarnya.
Matinya teknologi menangkap tradisional, seperti bubu dan bronjong, yang tersisa di toko kecil Putu Sinar dari Desa Tanggun Titi, adalah pertanda rusaknya ekosistim air di sekitar desanya. Teknologi ini tidak lagi diciptakan karena tidak telah kehilangan fungsinya. (*)
Penulis : Dr. I Wayan Artika (Akademisi Undiksha)