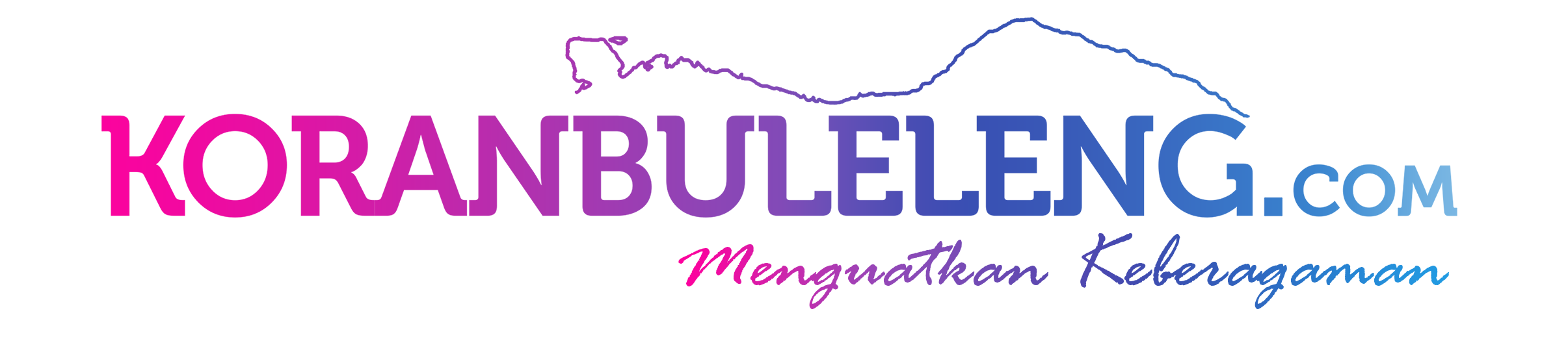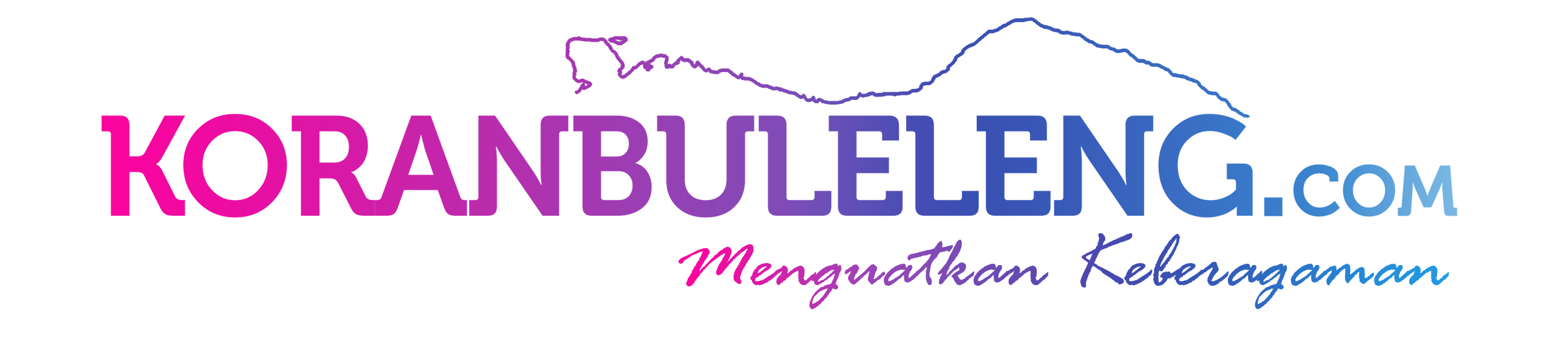Dr. I Wayan Artika, S.Pd., .Hum. |FOTO : Arsip|
SD No. 1 Batungsel dibangun awal tahun 1943 dan roboh oleh gempa Seririt (1976), baru beberapa bulan saya tercatat sebagai siswa kelas I. Saya gembira luar biasa karena bencana alam ini membuat sekolah libur beberapa bulan.

Tapi akhirnya saya kembali ke sekolah di bangunan darurat. Bangku-bangku sisa gempa dapat digunakan lagi. Begitupun meja guru dan papan tulis. Di tempat inilah saya melanjutkan penderitaan, paksaan atau tekanan, dan perundungan yang sama sekali dibiarkan oleh guru-guru saya.
Saya toh tetap harus “masuk” (sebutan untuk “sekolah”) dan selama di sekolah, kepala dipenuhi oleh keinginan untuk pulang lebih cepat. Saya tidak mengerti apa-apa soal sekolah. Saya ketakutan, tertekan, dan gemetar berhadapan dengan guru. Kelak saya tahu, hal ini karena saya masuk golongan murid “bodoh”, “kotor”, hanya anak seorang tani. Guru-guru saya lebih suka murid anak orang kaya, yang bajunya bersih, dan pintar.
Saya makin ketakutan dan tertekan ketika setiap membaca ke depan, pasti tidak kembali ke bangku, bahkan hingga waktu pulang. Sementara teman lain bercanda ria. Demikian pun ketika pelajaran berhitung. Saya selalu pulang paling akhir. Murid yang betul langsung pulang. Yang salah, seperti saya, tunggu dulu!
Kelak saya bertanya kepada masa lalu, mengapa guru-guru hanya bisa menyalahkan dan suka menghukum? Mereka tak pernah membimbing dan mengajari saya baca dan berhitung.

Bahkan suatu hari saya dipukul di punggung, sampai saya kencing di celana. Ini gara-gara cara saya menjawab soal perkalian 9×7, tidak sesuai dan bagi Bu Dewa Sukarni (guru saya), adalah cara orang bodoh. Saya tidak berani menatap wajahnya! Mungkin dia jemawa. Yang jelas, dia tidak tahu saya kencing, ketakutan, dan amat malu. Saya tetap menunduk, menahan air mata. Dia menghampiri teman-teman yang pintar dengan penuh kasih sayang.
Pada akhir tahun pelajaran semua siswa akan berpikir soal “naik” atau “lama” (tidak naik kelas). Saya sendiri tidak peduli karena tidak mengerti aturan main sekolah. Saya kira semua siswa secara otomatis “naik”. Saya juga tidak tahu apa arti kata “naik”.
Dalam bahasa Bali di desa saya (Batungsel), tidak ada kata “naik” dan saya sama sekali tidak tahu bahasa Indonesia. Pada hari kesaman (hari kenaikan kelas, penerimaan rapor) saya terima buku tipis warna hijau kusam, berisi tulisan yang tidak saya mengerti karena tidak bisa baca sama sekali. Buku ini saya pegang dengan hati-hati agar terjaga tangan saya yang kotor dan peluhan. Tetap tertutup. Sepanjang jalan orang bertanya, “Naik Gung?” Saya selalu jawab singkat “Naik”. Tapi pertanyaan ini tidak diajukan oleh orang tua saya. Saya simpan rapor di rak bambu atau langgatan. Saya kembali ke sekolah setelah liburan panjang selesai. Saya masuk ikut teman-teman di kelas sebelah karena kelas yang dulu diisi oleh murid baru.
Walaupun saya menderita karena guru tidak pernah membimbing saya, membenci karena saya murid bodoh, kotor, anak tani, tapi ada semangat kecil, “saya ingin bisa baca” sehingga tahu apa yang ada di balik tulisan buku pelajaran membaca di kelas II. Pengalaman buruk setahun lalu masih akan berulang dan baru berakhir satu setengah tahun kemudian. Atau, pada bulan-bulan awal di kelas IV (saya sudah bisa baca). Saya lancar membaca. Guru tentu saja mulai “kepincut”. Tapi mereka lupa, saya bisa baca bukan karena dirinya. Saya bisa perkalian atau “perpukulan” karena dilatih oleh bapak saya (Si Tani).
Namun demikian, saya tidak memiliki rasa dendam kepada guru-guru itu. Rasa dendam ini baru muncul kelak, belasan tahun kemudian, bermula di sebuah seminar matematika yang saya ikuti ketika di semester VI universitas. Saya dapat jawaban bahwa betapa bodoh dan terkutuknya guru-guru saya itu! Membenci siswa yang bodoh! Membenci siswa anak tani miskin! Hanya suka menghukum! Tidak pernah mengajari dengan sungguh-sungguh! Membenci siswa yang pakaiannya kotor! Tapi saat saya bisa baca di kelas IV, guru mulai menyangi saya tanpa rasa bersalah! Dan kala itu saya senang. Saya bisa menarik perhatian dan kasih sayang guru saya.
Ketika saya sudah bisa baca, iseng-iseng saya buka kembali rapor. Saya terkejut, karena sebenarnya tidak naik dari kelas I ke kelas II. Tapi karena saya tidak mengerti arti kata “naik” dan juga karena tidak bisa baca serta tidak paham aturan sekolah, saya ikut teman-teman saja “pindah kelas” (naik ke kelas II). Saya kira pindah kelas ini sangat wajar karena ruangan di ujung bangunan sekolah yang dulu saya tempati diisi oleh murid baru. Dan, di ujung lain bangunan sekolah kelas VI tamat.
Buru-buru saya tutup. Ini rahasia seorang siswa SD. Kelak, menjadi anekdot yang sering saya ceritakan kepada mahasiswa atau peserta pelatihan dimana saya menjadi instruktur. Setiap kali diceritakan, pasti mengundang tawa.
Pengalaman buruk sebagai siswa yang dibenci guru, dipukul hingga kencing di celana, dipermalukan di depan kelas karena hanya bisa baca tanpa mengenal huruf judul bacaan, “Gempa” atau “Lebaran”, menjadi bekal bagi saya ketika menjadi dosen. Saya pun memilih satu ideologi yang sangat tepat dan menjadi antitesis pengalaman itu, yakni ideologi pendidikan yang dikembangkan oleh Paulo Fraire, pendidikan yang berpihak kepada kaum miskin, yang membebaskan siswa dari penindasan. Saya merenung dalam, saat saya di SD, terutama, dari kelas I-IV, guru-guru menyelenggarakan pedagogi penindasan atau pedagogi hitam.
Namun demikian buruknya pengalaman saya, selanjutnya akan berjumpa dengan guru-guru yang penuh kasih sayang. Bu Sundari memberi saya cerita dalam pelajaran sejarah ketika di SLUB II Saraswati Tabanan. Pak Cawi membuka mata saya soal matematika. Bermula dari satu definisi, “bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi dua dan oleh dirinya sendiri”. Pernyataan abstrak ini melekat hebat dalam ingatan saya. Bapak Dewa Muliana memberi saya kepercayaan pada kemampuamenggambar lewat angka 8, atas gambar meja yang menggunakan perspektif. Di luar sekolah saya mengenal sastra dan teater dari Bapak Bawa Samargantang.
Hubungan kesetaraan guru dan siswa yang mudah saya pahami, diperoleh dari Bapak Ida Bagus Widasna di Saraswati 1 Tabanan. Kemandirian dan kebebasan saya dapat dari kepala sekolah saya di SMA (Saraswati 1 Tabanan), Bapak Gusti Ngurah Putu Swastha. Ketekunan dan dedikasi hebat seorang guru senior berpengalaman internasional saya dapat dari Bapak Ngurah Raka Purwa dalam pelajaran Bahasa Jerman.
Di universitas, pascasarjana hubungan dosen dan mahasiswa pasti berbeda dengan di sekolah menengah atau SD. Di sinilah saya berjumpa dengan “guru-guru” berkarakter keilmuan yang sangat hebat. Jadi, itu beda guru dan dosen! Ketika saya menyampaikan rencana pernikahan, dosen saya memperlakukan saya sebagai anaknya sendiri. Beliau mengantar “menjemput” calon istri saya. Boleh kiranya saya dibenci oleh guru-guru saya di SD, namun di SPM, SMA; dan universitas, saya berkesempatan mendapat pendidikan hebat dari para guru dan dosen yang terhormat. (*)
Penulis : Dr. I Wayan Artika, S.Pd., .Hum. (Dosen Undiksha, Pegiat Gerakan Literasi Akar Rumput pada Komunitas Desa Belajar Bali)