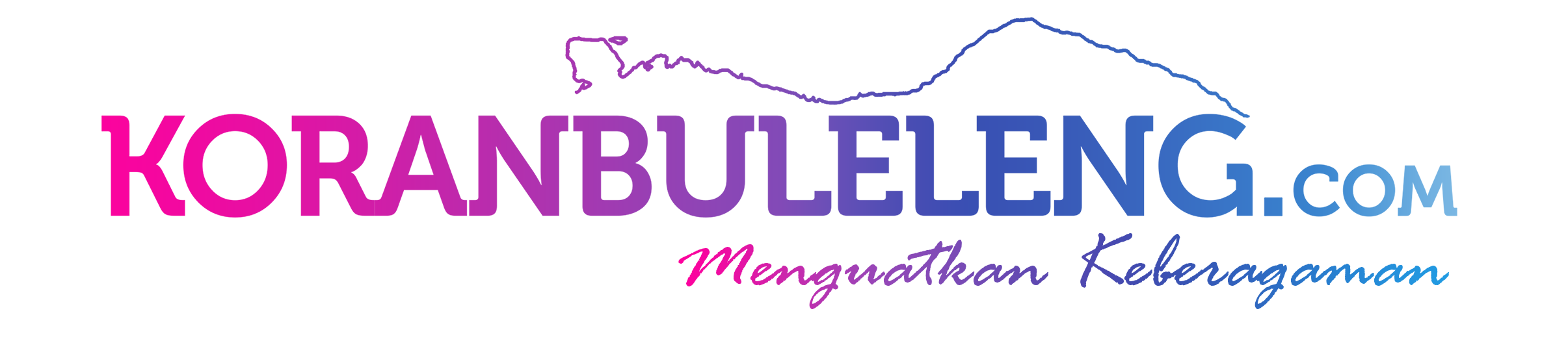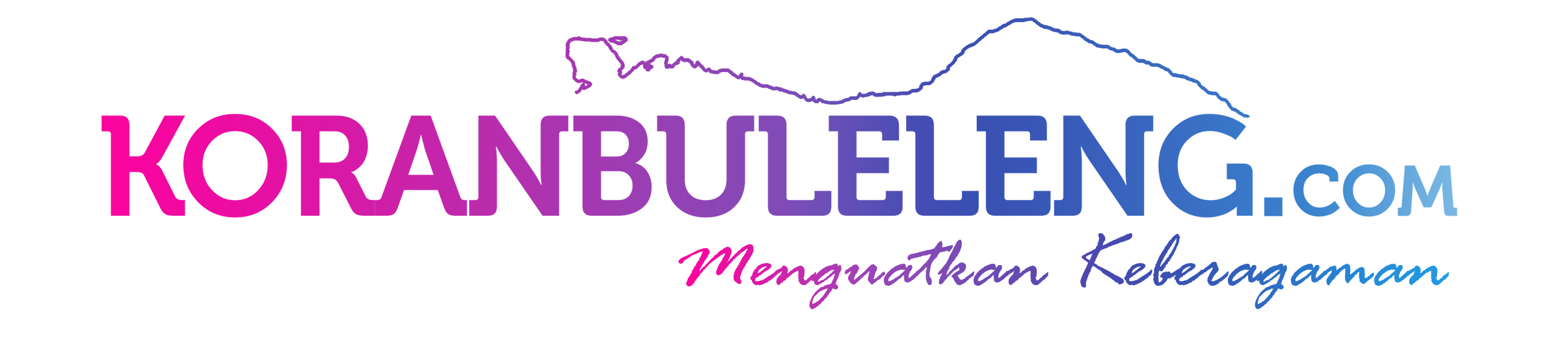Dr. I Wayan Artika, S.Pd., M.Hum.
Salah satu genre buku dengan objek karya seni. Biasanya tulisan mengenai karya seni adalah kritik. Tetapi buku-buku dengan objek karya seni tidak selalu demikian. Karya seni murni menjadi objek penulis. Banyak buku seni mendeskripsikan karya seni rupa apa adanya, dilengkapi foto yang sangat menarik. Buku seni bertujuan mengemas karya dalam bentuk buku, menghadirkan dalam lipatan-lipatan kertas, seperti buku-buku seri koleksi lukisan Presiden Soekarno. Karena itu, harganya sangat mahal.
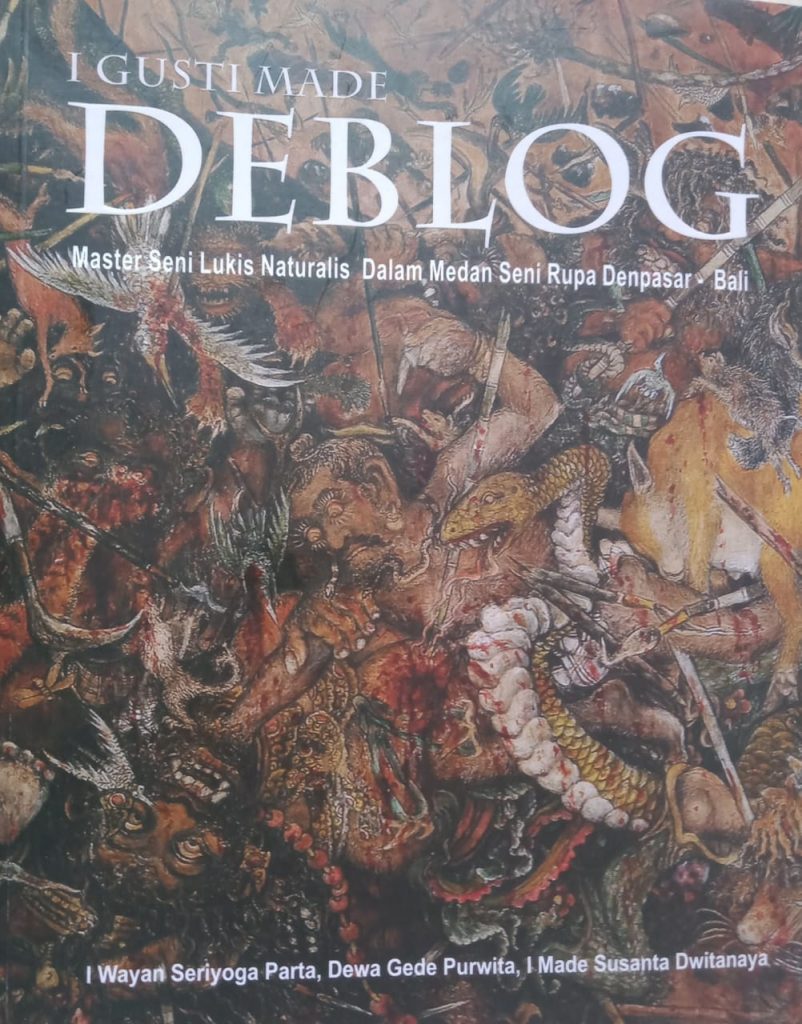

Buku seni memang tidak hanya menghadirkan karya tetapi juga memberi banyak informasi, seperti biografi, ideologi, konstelasi dan dinamika sosial, maupun aspek ekonomi. Buku I Gusti Made Deblog, Master Seni Lukis Naturalis dalam Medan Seni Rupa Denpasar-Bali (Komunitas Gurat Institut, 2020) mengandung pengetahuan mengenai posisi Denpasar dalam sejarah seni rupa Bali. Buku ini menjelaskan bahwa selama ini Denpasar tidak tercatat. Karena sinergi pariwisata dan seni yang berpusat budaya Ubud dan sekitarnya, maka menjadi pusat wacana seni lukis Bali. Hal ini adalah konsekuensi produksi wacana yang dipengaruhi oleh aspek-aspek luar, seperti industri.
Dari segi itu, peranannya sangat penting. Buku ini mengalihkan perhatian masyarakat dari wacana seni rupa pariwisata di Ubud dan sekitarnya menuju Denpasar. Jika produksi wacana sebagai yang dominan maka dengan buku ini, para penulis telah menghadirkan wacana tandingan dalam sejarah seni rupa Bali lewat seorang Master, I Gusti Made Deblog.
Buku ini memang berada dalam arus utama gaya wacana buku seni yang elit atau mahal, tidak hanya dalam kemasan tetapi uraian atau sudut pandang para penulis. Seni rupa Bali tumbuh dengan sendirinya, berdampingan dengan kegiatan ekonomi pertanian dan kehidupan masyarakat yang menganut mitos-mitos asli yang kelak bersandingan dengan dunia Hindu dengan khazanah panji Jawa, epos, dan tantri.
Tapi kelak dengan datangnya seniman Barat bersamaan dengan kolonialisasi; mengapa para kritikus seni rupa dan para penulis buku seni terlalu gemar menelisik pengaruh luar dalam karya-karya seniman setempat. Seorang penulis akan sangat senang jika sanggup mengungkap seorang pelukis setempat menerima pengarus seniman barat. Hal ini penting dibicarakan mengingat kedatangan pelukis barat di Bali serangkaian dengan kolonialisasi di Asia Afrika. Perspektif poskolonialisme menjelaskan bahwa pengaruh yang dibangun pada diri seorang seniman lukis di Bali ada dalam kerangka agen dan objek: penjajah dan terjajah. Posisi-posisi inferior selalu ditempati oleh seniman Bali ketika berhadapan dengan seniman Barat. Tidak pernah dikonstruksi pembalikan posisi bahwa pelukis barat yang datang ke Bali adalah kaum inferior. Sudah jelas alasan kedatangan dan menetap di Bali bahwa pulau ini memiliki kekayaan budaya yang melebihi barat yang sama artinya posisinya lebih tinggi, demikian pula penduduknya. Namun, ironis, di Bali mereka didewakan.

Dalam buku ini dijelaskan bahwa I Gusti Made Deblog mendapat pengaruh dari seniman China. Pendekatan poskolonial tidak bisa diterapkan karena hubungan politik penjajahan di antara Bali dan Cina tidak ada. Karena itu, buku ini menjadi sangat penting karena menandingi wacana kolonialisasi yang dialami oleh seniman-seniman Ubud dan sekitarnya. Mereka bangga di bawah pengaruh seniman-seniman Barat. Sementara itu di Denpasar hidup seniman-seniman lukis yang bebas dari kolonialisasi. Dari perspektif poskolonialisme penulisan seni rupa, buku ini antikolonialsme dan karena itu menjadi buku yang sangat penting. Seni rupa Bali membutuhkan wacana-wacana untuk melawan kolonialisme. Wacana tidak ada secara netral. Wacana adalah alat. Wacana dapat digunakan untuk melawan wacana yang sudah ada dan berpengaruh.
Hal lain yang merupakan konvensi penulisan buku seni rupa adalah menggunakan karya sebagai medan membangun teks verbal (bahasa, linguistik, sastra, mitos, agama, epos). Setiap karya yang dibicarakan selalu dipahami atau dijadikan medan teks verbal. Buku ini sebenarnya menegaskan posisi seni rupa di antara cabang seni lain, khususnya hubungan sastra dan mitos dengan seni rupa itu sendiri.
Hubungan ini telah dijelaskan oleh M.H. Abrams dalam bidang sastra, terutama salah satu dari keempat pendekatan dasar sastra: hubungan sastra dengan semesta. Karya-karya I Gusti Made Deblog lahir dari adanya hubungan seni dengan semesta Bali (mitos, panji, epos, dan tantri). Hal ini dibuktika melalui pembahasan yang terperinci oleh Adrian Vickers (hal. 159). Teori Abrams tidak hanya menjelaskan hubungan karya dan semesta. Masih ada teori eksprsif dan pargmatik. Vickers tidak menjelaskan alasan-alasan I Gusti Made Deblog memilih objek-objeknya sehingga mencipta hubungan dengan semesta. Demikian pula, lebih-lebih, aspek pragmatik karya-karya I Gusti Made Deblog. Sedangkan, pendekatan otonom dalam tulisan seni rupa memang sudah jauh lebih mapan dan pasti karena hal itu murni perkara teknik.
Para penulis seni rupa belum banyak yang menjelaskan suatu karya dengan pendekatan pragmatik dan ekspresif. Pendekatan pragmatik menjelaskan tujuan-tujuan suatu lukisan, seperti seri lukisan celeng Djoko Pekik, “Tanpa Bunga dan Telegram Duka”, “Susu Raja Celeng”, dan “Berburu Celeng” atau karya-karya instalasi Heri Dono.
Apakah I Gusti Made Deblog saat melukis sejalan dengan konsep Gao Xinjiang yang ketika menulis sastra adalah berbicara untuk dirinya sendiri? Apa tujuan melukis “Pedanda Baka”, objek dengan repertoar Tantri yang sangat terkenal di kalangan seniman Bali. Tulisan-tulisan dalam buku seni rupa Bali perlu bergeser dari tradisi mimesis menutju tradisi pragmatik dan ekspresif. Karya dibahas dari segi pribadi pelukis dan manfaat karya itu bagi masyarakat.
Lukisan dalam buku seni rupa, termasuk dalam buku ini, dijadikan medan bagi penulis untuk membangun teks yang sudah diketahui secara sosial, seperti umumnya bersumber dari sastra (epos dan Tantri).
Aspek konvensi penulisan buku seni rupa Bali juga tampak pada relasi “lisan” “tulis elit” “visual”. Bali mengawali sejarah sosial dalam tradisi lisan yang berlangsung lama, hingga Prasasti Blanjong ditulis, sebagai bukti memasuki periode sejarah. Sejak ini raja-raja Bali Pulina menulis di atas lempeng tembaga, kelak lontar ditulisi, menghasilkan naskah yang sangat melimpah. Pada masa tradisi lontar, penyebaran aksara Bali mulai meluas namun tertahan pada pusat-pusat kelompok yang berkuasa. Materi lontar, pengetahuan yang menyangkut seluruh aspek hidup masyarakat hanya dikuasai oleh kaum elit. Sehingga, masyarakat tidak pernah bergerak meninggalkan tradisi lisan. Justru konsekuensi sosial dan politik klaim penguasaan aksara, sastra, dan lontar, adalah buta aksara yang dibiarkan dengan konvensasi semakin masifnya masalisasi tradisi lisan. Masyarakat menerima pengetahuan melalui jasa kaum elit yang literat dan harus dibayar mahal, dan itu terjadi secara lisan. Masyarakat ditaklukan oleh politik tabu aksara. Barangsiapa yang membaca lontar akan gila. Sepanjang sejarah aksara Bali, orang Bali sesungguhnya buta aksara.
Dalam kondisi ini seni Bali (pertunjukan dan rupa) berperan sangat penting. Dalang tidak hanya menarasikan epos Ramayana dan Mahabarata tetapi juga telah memadukan dengan aspek visual, draturgi pedalangan, cahaya, dan tata suara atau musik. Para undagi atau sangging memahatkan pembuatan jembatan menuju Alengka oleh pasukan kera di tembok pura. Seniman Desa Kamasan melukis langit-langit Kerta Gosa dengan cerita Bimswarga. Kosmologi Bali divisualkan dalam padmasana yang berdiri di atas punggung kura-kura raksasa dan terlilit sepasang naga untuk kestabilan kosmik. Dari sinilah orang Bali memahami gempa bumi sebelum sain masuk dengan penjelasan pergeseran lempeng tektonik. Demikian pula tidak ketinggalan para pelukis. I Gusti Njoman Lempad menggambar seri cerita keluarga Brayut dan pada karya lainnya menceritakan kembali secara visual dukacarita Jayaprana. Konsep ini dengan sangat jelas tampak pada buku ini.
Terjadi dua jenis pembacaan karya seni rupa. Ada yang awam, melihat karya secara murni sebagai karya yang mengagumkan, seperti seorang anak yang “terkurung dalam poster film “Perang Vietnam”. Pembacaan lain yang terdidik di kampus-kampus seni, tidak lagi menikmati keindahan karya seni tetapi menjadikan karya ini medan untuk mebeberkan pengetahuannya. Tidak hanya itu, juga melakukan interpretasi atau penafsiran atas data-data visual, misalnya titik-titik atau bentuk-bentuk segitiga dalam karya Wianta, untuk sampai kepada makna. Karena itu, pembahasan karya seni didominasi oleh aspek ekstrinsik karya dan subjektif. Karya seni diposisikan di bawah kuasa pengetahuan penikmat akademik. Hal ini pula dijadikan standar mutu karya oleh para kritikus kampusan.
Penikmat yang awam mengapresiasi karya seni dengan cara yang asli, murni, dan jujur, karya dimuliakan dan diposisikan terhormat. Tidak ada keangkuhan untuk menguasai karya seni dengan memandangnya dari pengetahuan yang dimiliki. Buku ini sudah jelas bukan hasil pembacaan awam yang terpukau kepada karya-karya sang master tetapi pembacaan ekstrinsik (historis, biografis, mitos, epos, tantri, dan panji, pariwisata, dan kolonialistik). Pembacaan ini seolah-olah mengagumi karya tetapi hal ini semu karena karya hanya tumpuan untuk mengkonstruksi pengetahuan luar di atas ruang karya.
Buku ini menegaskan apa fungsi seni di Bali. Seni di Bali bukan uniti atau entitas parsial tetapi dalam kerangka menjalankan fungsi sosial sebagai media antara dunia kata (mitos, Hindu) menjadi dunia visual: fisik. Kelak, kehadiran pelukis barat di beberapa desa penting di Bali mengubah fungsi seni lukis dengan adanya pemurnian atau pembersihan lukisan dari fungsi-fungsi asli. Sebenarnya inilah sebuah wujud kolonialisasi yang tidak pernah disadari oleh kalangan seniman Bali.
Model kolonialisasi berselubung kesenian dengan para penjajah atau bandit-bandit barat berhasil mengubah paradigma seniman Bali yang menjadi hamba dan ngayah, mempersembahkan karya kepada masyarakat; menjadi pribadi-pribadi baru dengan mental ikut-ikutan menjadi kolonialis. Pikiran menjual karya mulai tumbuh dan menjadi tujuan hidup seniman. Pikiran mulai ingin menjadi individu yang lepas dengan individu lain dalam kesadaran tinggi komunlisme, mulai merasuki para pelukis. Karya-karya yang seragam mulai dihindari dan dipandang rendah.
Maka, buku-buku kajian seni rupa Bali saat ini harus dengan sadar memegang prinsip-prinsip poskolonial. Buku-buku seni harus mengembalikan para seniman kepada kesadaran Bali yang hidup dalam komunalisme desa adat yang murni tanpa pernah mereduksi sebuah karya seni dari fungsi sosial. Kajian-kajian poskolonial memberi kesadaran baru bahwa seni lukis modern yang masuk lewat kaki-kaki agen kolonial bukan kemajuan tetapi sebaliknya, kekalahan bangsa terjajah. Ketika buku ini beralih ke Denpasar, dengan sendirinya peran seniman Barat tidak disinggung secara khusus, maka buku ini sedang dengan tidak sadar melakukan produksi wacana antikolonialisme. Dalam kesadaran poskolonial, pandangan dan sikap tersebut, yang tebersit dalam buku ini adalah hal yang sangat penting.
Buku-buku tentang seni lukis, harus memutus mata rantai pengaruh barat dan pemujaan antek-antek seniman kolonialis di alam Bali. Bali hari ini harus disadari bukan terbentuk karena modernisasi kolonialis tetapi harus dipandang sebagai garis sejarah yang terus bergerak. Di dalam alam ini seni lukis Bali tetap pada spirit yang tidak dipengaruhi oleh dunia barat. Bali tidak pernah menerima pengaruh luar, sebaliknya seniman asing-lah yang memasukkan dirinya dalam pengaruh seni lukis Bali.
Penulis : Dr. I Wayan Artika, S.Pd., M.Hum., Dosen Undiksha, Pegiat Gerakan Literasi Akar Rumput pada Komunitas Desa Belajar Bali