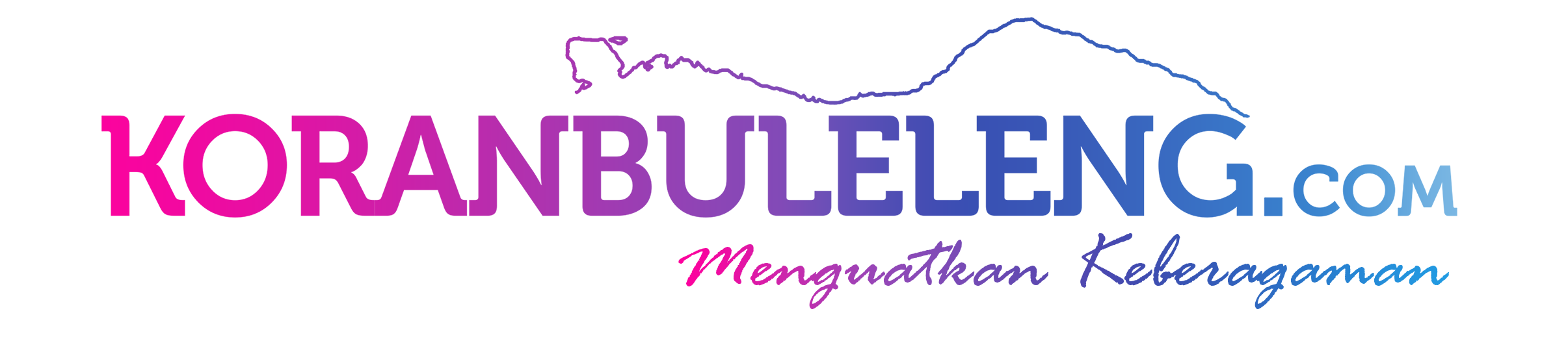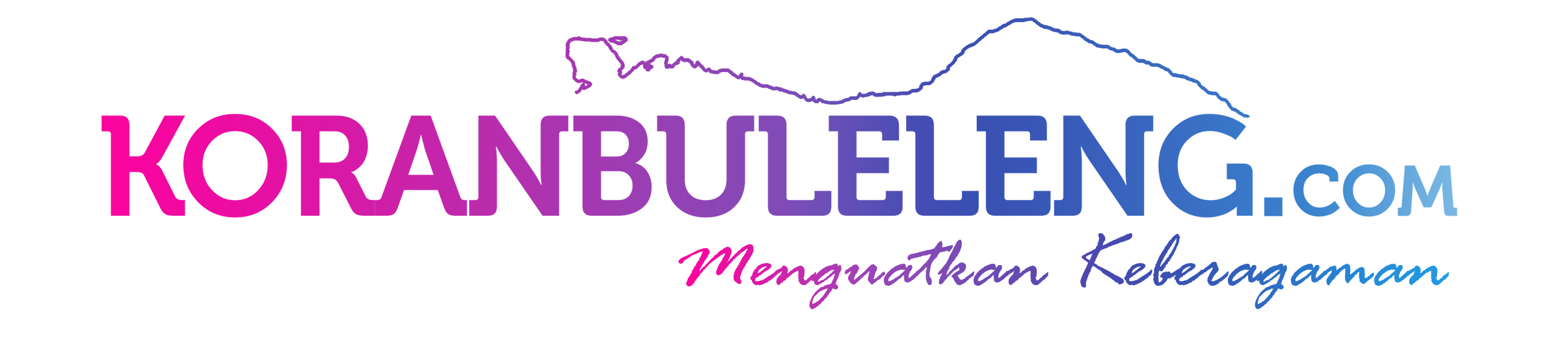Lagu “Sing Pocol Nyentana” tidak hanya menyindir pisaga yang resek tetapi lebih daripada itu mengembangkan cara pandang baru yang lebih rational: tresna, rasionalisasi biologis, dan ajin raga (harga diri laki-laki) jangan dicampuradukkan, bro!
Tulisan ini menyinggung beberapa poin kruasial kehidupan orang Bali, seperti purusa (harga dri tinggi laki-laki), anak, dan hukum perkawinan. Purusa adalah hukum yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan scond sex. Kedudukan laki-laki dalam segala hal lebih tinggi, baik di keluarga maupun di masyarakat.

Perkawinan yang diatur oleh ideologi purusa dilaksanakan dengan cara-cara yang dalam perspektif gender dan patriarki, praktik ketidakadilan berat terhadap kaum perempuan. Mereka meninggalkan rumah orang tuanya (umah bajang). Anak perempuan tidak ada dalam daftar penerima harta warisan keluarga. Perempuan meninggalkan keluarganya dan menghapus semua jejak niskala-nya dalam upacara mapamit.

Puncak haru dan berair mata (seperti sebuah postingan di media sosial yang sering dirujuk) dalam upacara perkawinan adalah ketika perempuan pamit meninggalkan keluarganya baik secara adat maupun niskala. Sejak itu, ia tidak lagi anggota keluarga asalnya. Ia menjadi keluarga baru di rumah suaminya. Seperangkat banten disiapkan dalam upacara mapamit di sanggah keluarga besar. Mapamit atau mohon izin untuk pergi memiliki makna untuk meminta izin kepada para Dewa, Ida Betara, sesuhunan, dan leluhur bahwa yang bersangkutan tidak lagi bersujud dan menyembah. Sujud dan sembah baktinya berpindah ke dewa, ida betara, sesuhunan, dan para leluhur suaminya.

Sebagai adat atau hukum sosial, upacara mapamit atau yang terkesan sebagai “mengusir” perempuan dengan pengesahan-pengesahan suci (adanya banten, mantram, dan saa), wajar terjadi atau dilakoni jika oleh perempuan karena mahluk kelas dua yang lebih rendah ketimbang laki-laki. Praktik mapamit pada laki-laki Bali tentu bertolak belakang dengan kuasa purusa.
Mapamit dalam nyentana merupakan pengalaman adat yang paling memalukan bagi laki-laki. Mapamit menjatuhkan laki-laki Bali ke titik nadir sosial. Karena itu, tidak ada laki-laki yang mau mengalaminya dalam kehidupan, maka dan ini satu-satunya jalan: jangan memilih pernikahan nyentana. Namun dalam lagi “Sing Pocol Nyentana” nyentana sama saja dengan perkawinan biasa: memberi kebahagiaan. Dek Artha, penulis lagu ini, bersikap lebih santai dan rasional: lakukan saja atas dasar cinta yang tulus, jangan campuradukkan harga diri, bukan untuk mengejar harta, dan keadaan di keluraga laki-laki memungkinkan (memiliki nyama muani lebih, bersaudara laki-laki cukup). Tekanan pentingnya adalah, fokus dengan keluarga istri dan jangan hiraukan pisaga yang resek.

Nyentana menukar posisi laki-laki menjadi perempuan dan perempuan menjadi laki-laki. Laki-laki meninggalkan keluarganya dan sanggah beserta semua pura atau tempat suci di keluarga sendiri dan mendapatkan yang baru di keluarga istri. Laki-laki yang nyentana mengalami persoalan-persoalan psikologis terutama ketika berhadapan dengan lingkungan atau pisaga. Hal ini disindir dengan sangat pedas dalam lagu “Sing Pocol Nyenta” (pencipta Dek Artha, penyanyi Dek Pekir), pisaga lebih resek, sek, sek. Penulis lagu ini menggunakan kata “resek”, diulang “sek, sek sek” sebagaimana cara orang Bali mengusir anjing. Sindirian ini amat pedas, pisaga atau tetangga adalah anjing. Jadi jangan dihiraukan, asal mertua baik. Niat tulus dan cinta seorang laki-laki untuk nyentana sering kandas karena tetangga yang resek, suka menggonggong seperti anjing. Maka lagu ini menyatkaan “sek, sek, sekkk”, anjing kau tetangga!

Cikal-bakal perkawinan nyentana karena adat Bali tidak bisa mengatasi kenyataan pada keluarga-keluarga hanya melahirkan anak-anak perempuan. Di masa depan keluarga ini akan habis secara purusa. Semua anak-anak perempuan pergi meninggalkan orang tuanya. Walaupun di keluarga-keluarga suminya mereka beranak-pinak, para cucu atau keturanan tersebut tidak bisa dipandang sebagai penerus. Lalu semua harta atau warisan akan beralih ke keluarga terdekat (saudara ayah, sepupu), demikian seterusnya, akan diambil alih keluarga besar dengan “dalih” biaya upacara dan cost tanggung jawab sosial. Agar masalah ini tidak terjadi maka dibuatlah sistem perkawinan tandingan: nyentana.
Dalam praktik sosialnya, nyentana tidak mudah! Ada hambatan sosial yang harus diatasi oleh keluarga yang ingin memilih jalan ini. Tapi lagu ini memiliki pandangan sebaliknya. Nyentana itu tidak ribet asal tresna, rasional, jauhkan motif ekonomi, dan jangan hiraukan tetangga.
Keluarga besar biasanya tidak mudah menerima karena ada kecemburuan adat. Ia dipandang bukan sebagai orang yang tulus untuk nyentana. Justru dituduh matre. Poin ini muncul di dalam lagu ini sebagai pembelaan sosial bahwa tidak zaman lagi laki-laki nyentana untuk kaya dengan mudah dan cepat. Masyarakat atau pisaga tidak mau tahu, bagaimana beratnya keputusan yang diambilnya sampai dia mau nyentana (menahan rasa malu, bernegosiasi di keluarga baru, meyakinkan keluarganya sendiri agar dizinkan, mencoba tetap lebih rasional menghadap sistem intelektual adat yang penuh dengan kontradiksi logika).
“Sing Pocol Nyentana” justru mengembangkan sikap yang lebih “santai”; jika cinta lakukan nyentana dan jangan hiraukan gonggongan tetangga atau pisaga yang resek. Anggap saja mereka kaum anjing (sek, sek, sek). Lalu soal harga diri (ajin raga), menurut lagu ini, jangan dicampuradukkan. Nyentana tidak ada kaitan dengan harga diri seseorang karena syarat utama yang tidak bisa ditawar: cinta (trensna) yang tulus. Dek Artha mungkin juga sudah muak dengan klaim sosial bahwa seorang laki-laki nyentana selalu dituduh bermotif harta dan obral harga diri.

Walaupun tidak diterima sebagai jalan yang “benar” seperti halnya perkawinan biasa, nyentana tetap ada karena orang Bali selalu menghadapi benturan konsep biologi melawan kultur. Dari sisi kultural, orang Bali boleh berpikir hanya mengutamakan laki-laki namun dari sisi biologis, ada kalanya di dalam banyak lekuarga hanya lahir anak perempuan. Bali dengan pendidikan modern Barat pola pikir lama mulai berubah meskipun tidak tampak secara radikal dan cepat. Bali ada dalam dinamika ideologis proses revisi atau dekonstruksi ideologi purusa.
Di dalam dinamika tersebut, muncul praktik-praktik aneh. Kakek mengangkat cucu menjadi anak. Cucu (biasanya dipilih yang laki-laki) di-peras atau diadopsi secara kuno menjadi anak oleh kakek-neneknya.
Terjadi pula kejahatan dengan menjebak seorang laki-laki. Si perempuan sengaja menjalankan suatu aksi sosial yang sangat rasional untuk menemukan laki-laki yang mau memacarinya dan tidur bersama, sampai dirinya hamil. Lantas pihak keluarga menggelar upacara perkawinan semu yang sangat murah dan sederhana hanya untuk menunjukkan bahwa anak dalam kandungan putrinya sah dan memiliki ayah sehingga kelak tidak disebut panak bebinjat (anak haram) sehingga semua praktik adat yang baik jatuh kepadanya. Setelah itu, mungkin sebelum anaknya lahir, si laki-laki atau si ayah semu bisa meninggalkannya. Akan menjadi berkah bagi keluarga perempuan jika anak itu seorang “pangeran”.
Perkembangan sistem perkawinan nyentana yang lebih modern dan akademik mulai dikenal dan dikaji secara ilmiah dengan merancang sistem perkawinan pada gelahang. Perkawinan ini adalah perkawinan setengah nyentana. Pada gelahang atau negen dadua mencoba untuk adil dan rasional mengingat sistem perkawinan nyentana belum bisa melakukan rekayasa sosial. Maka sistem perkawinan ini diharapkan merupakan rekayasa sosial di Bali dalam mengatasi keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki dan agar bisa hidup berbahagia dan tenang tanpa tekanan sosial.
Dalam hal ini kaum perempuan tetap berstatus ada di umah bajang. Sementara itu, yang laki-laki tidak sepenuhnya meninggalkan keluarganya sebagaimana dalam sistem nyentana. Sistem perkawinan pada gelahang atau negen dadua menekankan kepada seorang laki-laki untuk bertanggung jawaab secara purusa di dua keluarga.
Rupanya Dek Artha hendak menghadirkan satu pandangan kritis ala kaum milineal terhadap persoalan dan pergulatan orang Bali dalam sistem perkawinan nyentana, yang antara ada dan tiada. Lagu ini mencoba rasional dan resistensi terhadap pisaga (bentuk individualisme baru di Bali) dengan tetap memegang prinsip tresna (cinta), menolak untuk menjadi cowok matre, demi pernikahan bahagia. (*)
Penulis : Dr. I Wayan Artika, S.Pd., M.Hum. (Dosen Undiksha, Pegiat Gerakan Literasi Akar Rumput pada Komunitas Desa Belajar Bali)