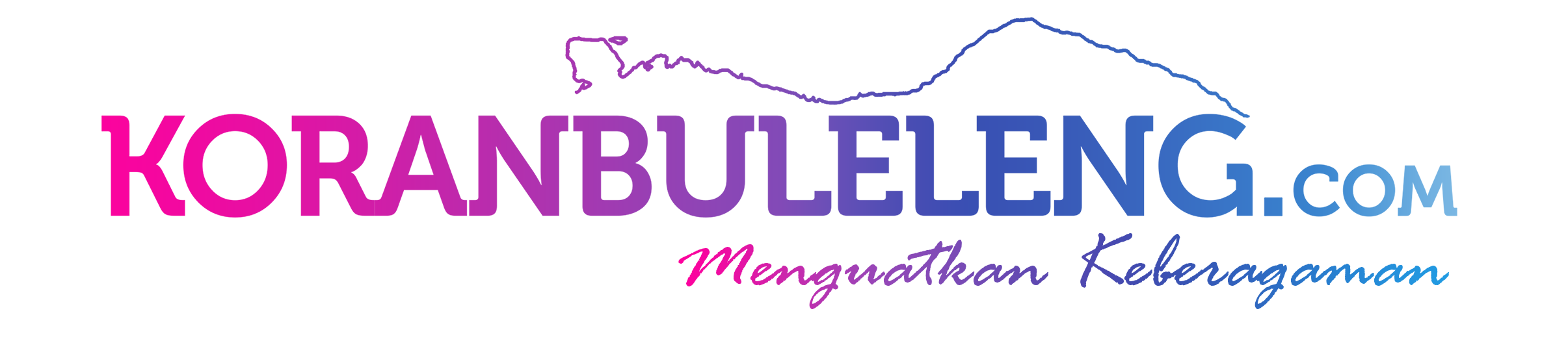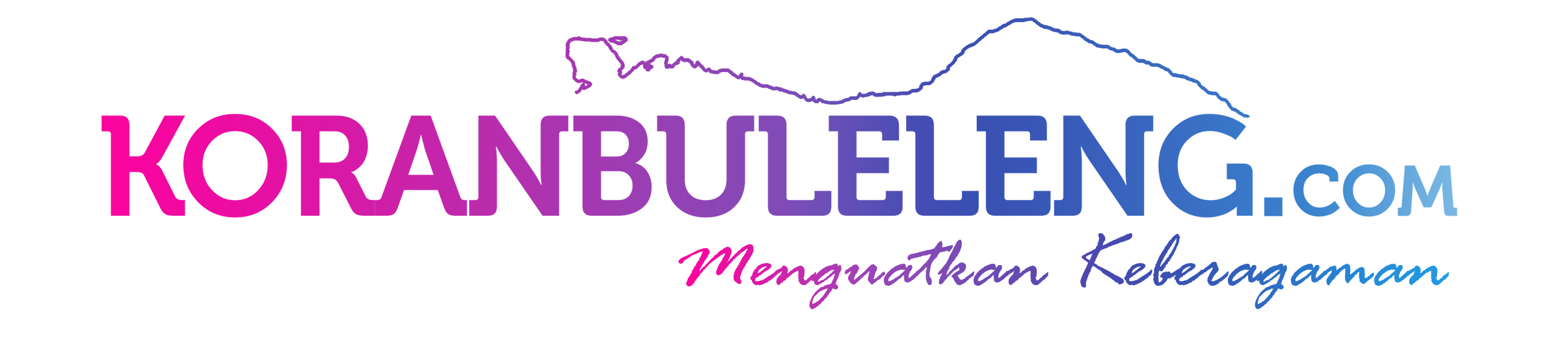Pada akhir dekade 1980-an, tidak sengaja bertemu buku tebal di perpustakaan SMA Saraswati 1 Tabanan. Buku ini berilustrasi sampul beberapa sosok tentara Dai Nipon. Postur kecil-kecil mengenakan topi kain dengan rumbai di belakang dan saat dipakai akan menutupi tengkuk. Buku ini tidak habis dibaca. Masih sisa setengah.
Revolusi di Nusa Damai karangan K’tut Tantri.

Setelah di universitas bertemua satu buku berukuran kecil yang cukup tebal di perpustakaan di Kota Singaraja. Judulnya Revolusi di Nusa Damai. Buku ini ditulis dalam ejaan lama. Sampulnya gambar pulau Bali yang sedang dilanda gelombang samudera api. Di tengah pulau terdapat gambar meru menjulang ke langit.
Buku yang sama dari edisi yang berbeda.
Singkat kata buku ini usai dibaca dan menjadi buku penuh kenangan dan rasa kagum. Karena itu, paling sering dikisahkan di dalam berbagai kesempatan, seperti mengajar, memberi kuliah, dan pelatihan. Ada saja kesempatan untuk bercerita ulang potongan-potongan kisah dari Revolusi di Nusa Damai. Atau, sengaja mencari kesempatan untuk menceritakan buku ini di hadapan mahasiswa atau para peserta pelatihan. Sampai suatu siang di salah satu kelas SMP Laboratorium, seorang siswa kelas III angkat tangan dan berucap, “Saya juga sudah membaca Pak”, di akhir saya bercerita. Sungguh kejutan yang hebat! Seorang siswa SMP telah baca buku tersebut, di tengah iklim literasi sekolah yang morat-marit.
Pada setiap malam Natal, bagian akhir buku ini terasa sedemikian kudus. Tepat di malam Natal itu, pengarang buku ini, seorang perempuan Manx (Inggris) dengan kewarganegaraan Amerika, K’tut Tantri, tiba di Kota New York dan teman seperjalanannya adalah seorang mahasiswa Tionghoa; setelah 15 tahun tinggal di Indonesia. Ia berada di tengah-tengah New York yang bersalju dan dalam keadaan miskin. Lonceng berdentang dari menara-menara gereja untuk menyambut Natal di Metropolitan dunia. Di antara bintang-bintang di langit New York, K’tut Tantri menyaksikan satu bintang yang paling terang.

Pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan negara, buku ini kembali hadir dalam ingatan. Itu semua karena soal lupa dan melupakan. K’tut Tantri memang telah kembali setelah Indonesia benar-benar merdeka. K’tut Tantri terlibat langsung dalam perang-perang mempertahankan kemerdekaan bersama Bung Tomo dan Arek-arek Surabaya.
Esai ini untuk mengenang K’tut Tantri, seorang asing yang membantu perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Ada banyak kisah keterlibatan dirinya dalam diplomasi internasional membantu Presiden Soekarno agar sebuah negara baru yang bernama Indonesia dapat diterima dan diakui kemerdekaanya oleh dunia Internasional. Pada tahun-tahun masa akhir pendudukan Jepang, K’tut Tantri masuk Kamp Konsentrasi. Di penjara ini ia menjalani berbagai siksaan. Ia buang air besar di kamar selnya, berbagi ransum bersama kecoak-kecoak, dan meramal nasibnya dengan kartu-kartu yang dibuat dari pandan tikar alas tidurnya. Ia tahu akal-akalan tentara Jepang di halaman penjara; pura-pura menembak dengan senapan mesin. Tapi sejatinya kosong. Untuk membuat tahanan terkejut, bersamaan dengan letusan senapan, seorang tentara lain melepaskan “tembakan” dari ketapel.
Senja dengan gerimis jatuh di boulevard Hollywood. Poster film yang berjudul Bali the Last Paradise amat menarik minatnya. Dalam film ini, K’tut Tantri menemukan tanah impian, tanah yang dicari selama ini. Ia pun bulat tekad pergi ke Bali. Ia mengemas alat-alat melukis, buku-buku, dan bekal untuk keperluan selama dua tahun. Namun tidak! Seperti ia tulis di bagian awal Revolusi di Nusa Damai, dengan tulisan tangan asli untuk buku terjemahan dalam bahasa Indonesia; selama 15 tahun.
Ibunya tidak mampu membendung niatnya. Bagi ibunya, K’tut Tantri sama seperti ayahnya, yang lebih suka tinggal di negeri orang lain.
Ia meninggalkan Amerika dari pelabuhan New York dengan naik kapal barang menuju Timur Jauh, menghabiskan waktu kurang lebih selama tiga bulan. Inilah tempat dengan jarak yang paling dekat dengan Bali. Setelah singgah di Sanghai dan beberapa pelabuhan lainnya di Asia, kapal yang ditumpangi K’tut Tantri lempar jangkar di Batavia, yang saat itu ada di bawah penjajahan Belanda.
Walaupun telah berlabuh, ia tahu, tanah impiannya masih lebih dari seribu kilometer di sebelah timur. Maka, ia memutuskan menempuh perjalanan darat di jalan pantura Jawa mengendarai mobil yang dibelinya di Batavia. Ketika itu, jalanan masih banyak yang belum diaspal. Ketika kendaraan lewat debu nyaris menggulung kendaraan itu sendiri dan para penumpangnya. K’tut Tantri rupanya amat menikmati perjalanan ini. Pada malam hari ia meretas jarak sementara purnama menerangi jalanan.
Di tengah jalan, ia dicegat oleh seorang bocah dan ingin menumpang. K’tut Tantri antara kaget dan senang. Kaget karena mungkin Pito, demikian nama bocah di jalanan pantura Jawa ini; adalah umpan para penyamun. Senang karena Pito berbicara dalam bahasa Inggris seadaanya yang sangat sulit untuk dimengerti. Kurang lebih Pito mengatakan bahwa ia akan menjadi mulut, mata, dan telinga K’tut Tantri.
Di ujung timur Pulau Jawa adalah sebuah Kota Banyuwangi, menjadi titik penyebrangan menuju Bali dengan menggunakan perahau-perahu kayu yang dapat disewa. K’tut Tantri dan Pito menyebrangi Selat Bali dan bocah ini sedang tidur pulas di mobil yang sudah dinaikkan di atas perahu.
Sesampai di seberang, Pito bangun. Ia marah dan pada intinya tidak berani masuk Bali karena pulau ini penuh dengan leak. K’tut Tantri pun balik ke Banyuwangi, menyewa perahu bersama Pito. Di stasiun Ketapang yang berada di paling ujung Jawa, mereka berpisah. Perpisahan yang sangat mengharukan bagi K’tut Tantri. Pito memberinya jimat berupa buntilan kain untuk melindungi dirinya selama di Bali dari gangguan para leak. Saat itu, Pito mengatakan dirinya akan masuk tentara; ikut berjuang memerdekakan bangsanya dari penjajahan.
Dimulailah perjalananya di Bali, dari jalan-jalan di bawah rimbunan hutan Taman Nasional Bali Barat, melewati jembatan-jembatan kayu. Sepanjang jalan rama-rama menyabutnya dengan tarian. K’tut Tantri melukiskan warna kulit laki-laki Bali yang mengkilap seperti tembaga di bawah pancaran sinar matahari senja.
Belasan kilometer kemudian, ia tiba di desa-desa Bali yang indah dengan pura-pura yang atapnya bertumpang, pintu berukir, patung-patung, dan ukiran aneka motif di tembok-tembok bangunan dan rumah. Sampailah ia di Denpasar dan menginap di Bali Hotel. Hotel ini dipenuhi oleh orang-orang Belanda. Melihat kehadiran seorang kulit putih, orang-orang Belanda merasa terganggu karena mungkin agen mata-mata atau orang Eropa yang akan dapat menceritakan kepada dunia tentang keadaan Bali, bagian Hindia Belanda, dan penderitaanya di bawah kolonialisasi.
K’tut Tantri diintrogasi oleh petugas pemerintah Belanda. Ditanya ini dan itu, misalnya dimana akan tinggal selama di Bali. K’tut Tantri tentu tidak dapat menjelaskan karena dirinya belum tahu siapa-siapa di tanah impiannya. Namun begitu adanya, ia sudah merasa sangat bahagia karena setalah berlayar selama tiga bulan dan berkendaraan sejauh 1500 kilometer, akhirnya menginjakkan kaki di Bali.
Lantas, petugas-petugas Belanda ingin mengusir K’tut Tantri, bukan saja dari Bali Hotel tetapi dari Bali atau bahkan dari Hindia Belanda. Dengan demikian, praktik penjajahan buruk yang dijalankan oleh Belanda di Hindia Belanda tidak terusik.
Apapun yang terjadi, K’tut Tantri bergeming. Ia hanya bisa menjelaskan kemana tujuannya di Bali dengan menyampaikan bahwa dimanapun nanti bensin mobilnya habis maka di situlah tujuannya.
K’tut Tantri pun pergi meninggalkan Bali Hotel. Ia berkendara ke arah Timur. Dalam Revolusi di Nusa Damai memang tidak dijelaskan apa nama puri, tempatnya terdampar. Demikian pula nama-nama tokoh. Dari berbagai sumber menyatakan bahwa mobilnya kehabisan bahan bakar di depan sebuah puri di Kota Bangli. Di Puri mana ia terdampar dan diangkat menjadi anak keempat oleh raja, sama sekali tidak dijelaskan di dalam buku ini.
Di hadapannya tangga menjulang. Sayup-sayup terdengar suara asing dari orkes gong gede, nyanyian suci dari dunia kakawin, denting genta dari genggaman tangan para sulinggih pengiring mantra dan doa-doa, serta angin menebarkan harum aneka bunga tropis dan hio. Ia menapaki satu per satu anak tanggang itu. Sampailah ia di bagian atas, di sebuah pelataran puri yang sedang melangsungkan satu upacara besar yang mewah. K’tut Tantri merasa telah sampai di sebuah surga dan ia mengira dirinya telah mati.
Dalam keadaan bingung dan heran itu, seseorang menyapanya dalam bahasa Inggris. Dialah Anak Agung Nura, kakak angkatnya sekaligus kekasihnya yang menjelaskan bahwa dirinya sebagai anak raja, bersekolah di Negeri Belanda. Semula K’tut Tantri heran, di negeri yang berada di balik Inggris Raya, pada belahan bumi lainnya, ia berjumpa dengan seorang yang fasih berbahasa Inggris.
Di puri inilah K’tut Tantri tinggal untuk beberapa tahun. Ia mendapat perlakukan istimewa sebagaimana anak-anak raja dan anggota puri yang adalah kaum bangsawan Bali. Namun pada perasaannya yang terdalam ia ingin hidup bersama rakyat di tanah impiannya. Melalui perjuangan yang panjang, akhirnya ia diizinkan tinggal di antara rakyat.
Dengan dukungan penuh puri dan Anak Agung Nura, K’tut Tantri berhasil mendirikan hotel pertama di Pantai Kuta, yang bernama Suara Samudra. Selama di Bali, K’tut menemukan impiannya dan ia hidup di dalamnya sehingga masa mendekati 15 tahun tidak terasa dan lewat demikian cepat.
Karena perang dunia semakin bergolak dengan masuknya Jepang ke dalam kancah lewat Perang Pasifiknya, A.A. Nura ambil bagian untuk memerdekakan nereinya. Lantas K’tut Tantri meninggalkan Bali karena pasti tidak aman. Di Surabaya ia bergabung dengan Bung Tomo dan Arek-arek Surabaya.
Seperti sudah menjadi suratan, Pito benar-benar memenuhi janjinya, yang ia sampaikan ketika berpisah di Stasiun Ketapang, bahwa ia akan masuk tentara dan ikut berperang. Di kota Surabaya mereka bertemu kembali.
K’tut Tantri baru meninggalkan Indonesia setelah negeri ini benar-benar merdeka dan ia telah bertemu dengan para pejuang dan pemimpina nasional, termasuk Presiden Soekarno. Selama hidupnya, dunia mengenalnya dengan nama K’tut Tantri, nama yang diberi oleh seorang raja di Bali setelah ia diangkat sebagai anak kekempat di keluarga tersebut. Tidak banyak yang tahu siapa nama aslinya.
Dua paragraf akhir buku Revolusi di Nusa Damai mengabadikan kerinduan K’tut Tantri kepada Indonesia.
Dihari berikutnja aku mendapat uang untuk membajar uangnja kembali, dan membelikan pemuda itu (pemuda Tionghoa, penulis) sebuah tas, hadiah Natalnja jang pertama. Malam harinja aku mengantarkanja naik kereta api melandjutkan perdjalanannja ke Indiana, dimana ia akan beladjar. Kemudian aku bardjalan-djalan seorang diri, dengan perasaan rindu, ingin kembali ke Indonesia, karena kehilangan matahari dan udara hangat dan warna semarak dari dunia Timur. (*)
Penulis : Dr. I Wayan Artika (Akademisi Undiksha)