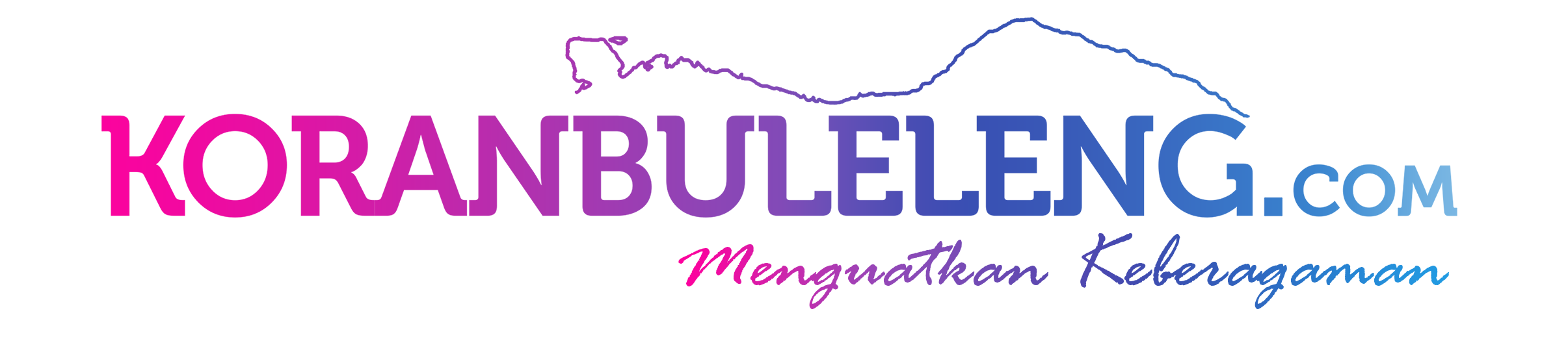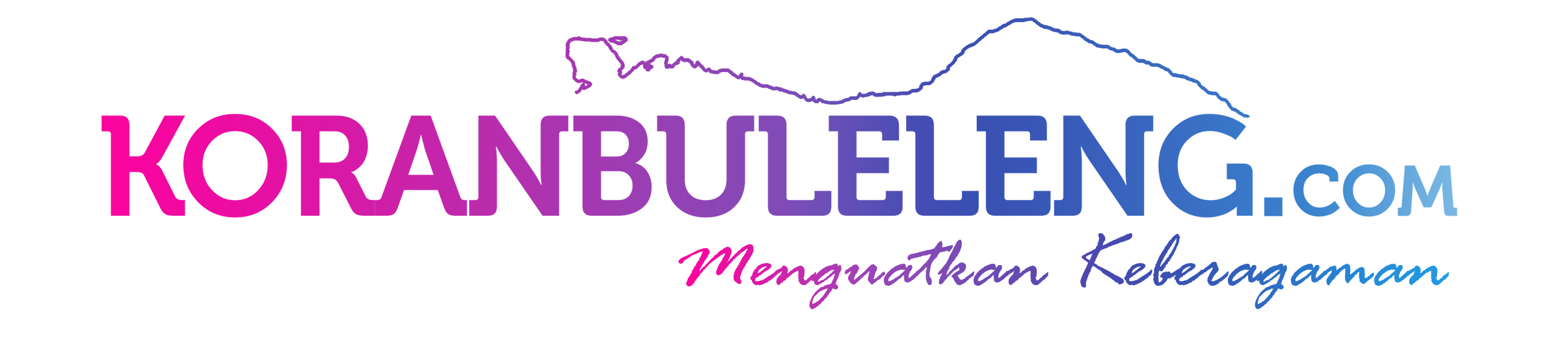Lewat medsos, tersiar kabar, setahun lalu, sebuah SD hanya mendapat seorang siswa. Ini terjadi di Kabupaten Jembrana. Tulisan ini seharusnya dapat memberi informasi, apakah sekolah itu tetap mengajar siswa bersangkutan?
Karena tidak memiliki informasi maka tulisan ini menyatakan sebagai berikut. Mungkin saja siswa tersebut tetap diperlakukan selayaknya. Ata dipindah ke sekolah terdekat lain. Jalan pintas yang dianggap paling masuk akal. Demikian dua kemungkinan yang ada. Kalau sekolah itu memilih bahwa siswa itu tetap diajar sebagaimana pada galibnya, maka akan ada cerita seperti berikut.

Ia tidak punya kawan bermain di kelasnya sepanjang tahun. Rasanya sangat menyedihkan kalau di kelas hanya ada seorang siswa. Karena sekolah dasar atau sekolah pada tingkatan manapun tidak mungkin lepas dari hubungan sosial. Mungkin ia punya teman kakak kelasnya. Ini berkaitan dengan kesepian dan keharusan. Di kelasnya hanya ada satu bangku yang terisi dan itupun hanya oleh seorang.
Dari sisi guru serupa ini, kurang lebih.
Gurunya mengajar secara individual dengan fokus kepada siswa tersebut. Si guru mengenal dengan sepenuhnya dan seutuhnya anak yang satu-satunya ini. Selayaknya anak sendiri. Metode mengajarnya pas karena hanya perlu satu metode yang paling hebat untuknya. Hanya untuk satu orang siswa yang sudah jelas gaya belajarnya. Komunikasi guru sangat intim. Guru dapat mengenali kemajuan belajar siswa secara cermat dan tidak perlu membuat alat evaluasi formal. Cukup assessment autentik saja. Evaluasi juga bisa berlangsung sepanjang hari sepanjang bulan, dan tahun.
Siswa ini sangat beruntung dan diistimewakan. Bayangkan dia mendapatkan pelayanan seorang diri, penuh. Iya mendapatkan perhatian guru paling maksimal. Guru juga dapat merancang program belajar yang sangat khusus dan spesifik. Singkat kata, ini adalah kondisi yang paling ideal dalam pendidikan manusia.

Tetapi itu semua dianggap ancaman bagi pendidikan atau sekolah dinilai gagal. Esai ini mencoba membahas jumlah siswa dalam satu kelas.
Semasa Orde Baru jumlah siswa SD sangat banyak di setiap desa di Indonesia. Pak Harto (Soeharto) yang ketika itu adalah presiden II Republik Indonesia membangun SD Inpres di seluruh peolosok. Di satu desa yang sempit misalnya ada tiga SD. Gedungnya dibangun di tanah sumbangan warga. Karena KB sukses jumlah siswa SD di desa-desa semakin tahun semakin menyusut. Hal ini juga terjadi karena urbanisasi pasangan muda ke kota. Anak-anak mereka seusia SD tidak sekolah di desa tetapi di kota-kota di mana orang tuanya bekerja.
Namun ada keadaan lain. Karena biaya hidup yang sangat mahal di kota maka di beberapa desa di Bali; anak-anak mereka di sekolahkan di desa asal dan diasuh oleh kakek atau nenek. Ini pilihan yang sangat logis secara ekonomi namun berisiko pedagogik. Jumlah siswa yang semakin sedikit di suatu desa banyak SD yang digabung atau regrouping. Lahan dan bangunan sekolah beralih fungsi atau mangkrak.
Guru-guru mendapat masalah dari kondisi ini. Mereka tidak nyaman mengajar seorang anak. Maka tak aneh jika guru-guru sering mengeluh bahwa jumlah siswa di sekolahnya sedikit antara 5 sampai 10 orang. Padahal ini kondisi yang ideal dalam pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh guru kepada murid.
Tapi guru lebih merasa berkuasa dan terkenal di hadapan kelas yang penuh sesak dengan siswa. Guru dapat pamer kuasanya. Guru dihormati bak aktor sandiwara. Guru menerima salam yang riuh dan merasa sukses menaklukkan dan mengatur keadaan kelas. Guru dapat mengalihkan dari suara ribut pasar menjadi hening senyap ruang meditasi sebuah kuil Budha. Semua itu membuat guru bersemangat sepanjang hari. Guru merasa mendapat tantangan terutama dalam mengelola kelas. Pokoknya guru mendapatkan eksistensi di hadapan siswa yang banyak.
Jumlah siswa di suatu sekolah berhubungan dengan angkatan kelahiran. Ini berkaitan dengan jumlah penduduk yang masih sedang produktif melahirkan. Jadi ini bukan kuasa sekolah. Sekolah hanya bertugas menyelenggarakan pendidikan. Untuk sekolah yang berbasis di desa seperti PAUD/TK atau SD di desa-desa maka jumlah siswa tidak penting diperdebatkan atau dipersoalkan lagi. Jumlah siswa tak bisa dijadikan standar penyelenggarakan pendidikan. Sekolah dipersiapkan untuk menghadapi berbagai kondisi demografis. Jumlah siswa entah memadai, anjlok, atau nihil. Guru hanya menyesuaikan diri dan berinovasi dalam mengajar.
Jumlah siswa tak bisa dikaitkan dengan beban kerja guru karena mengajar satu atau 30 orang bebannya sama. Ketika banyak desa mengalami kejadian seperti di desa Blimbingsari yang diunggah di media sosial, maka sejak 20 tahun lalu guru-guru membincangkan jumlah siswa yang cenderung menurun dan sepertinya mereka kurang terima. Sebenarnya Mereka menginginkan jumlah siswa yang banyak. Padahal ini melelahkan. Ini tidak sangkil dan mangkus. Tapi karena hasrat kuasa sosial guru sangat besar maka guru lebih berharap mengajar siswa yang banyak. Guru sejatinya tersiksa dengan hanya siswa sedikit di kelasnya. Guru menderita oleh jumlah siswa yang satu orang saja yang harus mereka layani setiap hari sepanjang semester.
Sekolah pada awal tahun ajaran baru berlomba-lomba mencari siswa bahkan ada sampai rebutan. Zonasi mengatasi masalah ini. tapi yang sering memainkan sistem zonasi justeru sekolah dan orang tua. Terutama sekolah yang dulu adalah favorit dengan siswa pilihan. Guru-guru di sekolah ini ingin mendapat anak-anak pintar bibit unggul. Sementara itu orang tua yang memandang pendidikan dan sekolah sebagai kasta juga menginginkan anak-anak mereka mendapat sekolah yang favorit dan mereka memilih sekolah-sekolah semacam itu yang kebetulan ada di luar zona.
Lewat zonasi pemerintah ingin agar sekolah adil dan siap dalam menyelenggarakan pendidikan. Sekolah di salah suatu zona menerima kondisi-kondisi sosial ekonomi dan demografis masyarakat sesuai dengan zona itu. Demikian pula orang tua agar patuh kepada zonasi. Tapi zonasi belum mampu mengubah keangkuhan sekolah-sekolah dengan angka 1 seperti SD 1 SMP 1 atau SMA 1. Atau sekolah-sekolah yang stigmatis sekolah favorit atau sekolah top. Orang tua juga begitu. Ini khusus pada mereka yang memandang pendidikan sebagai kasta. Orang tua tipe ini memilih sekolah yang berkasta tinggi sehingga anak-anak mereka terangkat derajatnya. Untuk itu zonasi harus dilanggar. Sekolah-sekolah yang dibiayai oleh masyarakat mungkin masuk akal bekerja keras untuk mendapat murid yang banyak. Tapi sekolah negeri atau SD yang di biayai pemerintah tidak perlu melakukan itu.
Masyarakat juga jangan menilai sekolah dari jumlah siswanya. Zonasi adalah sistem yang disiapkan untuk memastikan sekolah siap menghadapi kondisi demografis apapun itu. Tugas sekolah menyelenggarakan pendidikan yang paling baik (inovatif, kontekstual, humanis, merdeka, literat, TPACK dan lain-lain) karena mengajar siswa 100 orang di suatu sekolah sama dengan mengajar satu orang siswa. (*)
Penulis : Dr. I Wayan Artika (Dr. I Wayan Artika, S.Pd., M.Hum. Dosen Undiksha, Pegiat Gerakan Literasi Akar Rumput pada Komunitas Desa Belajar Bali)