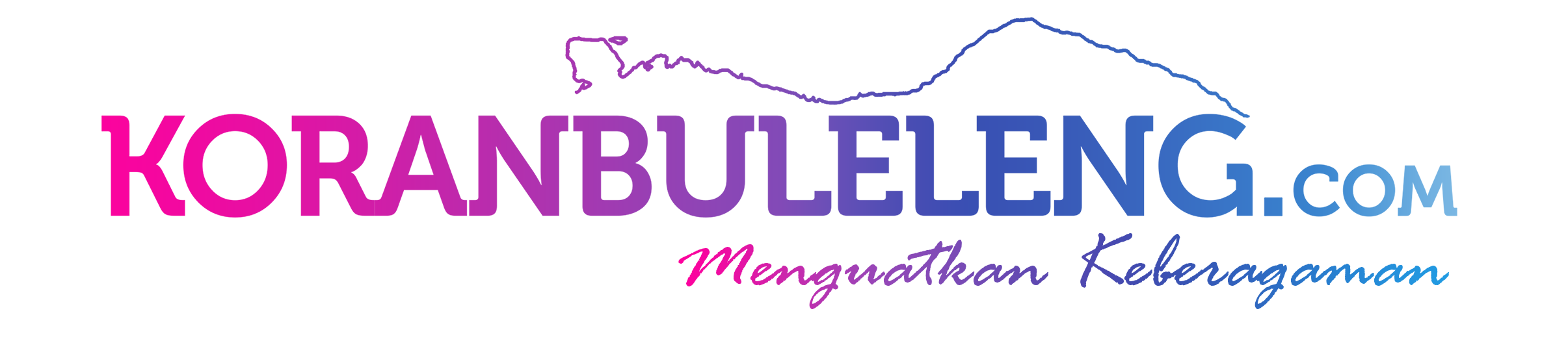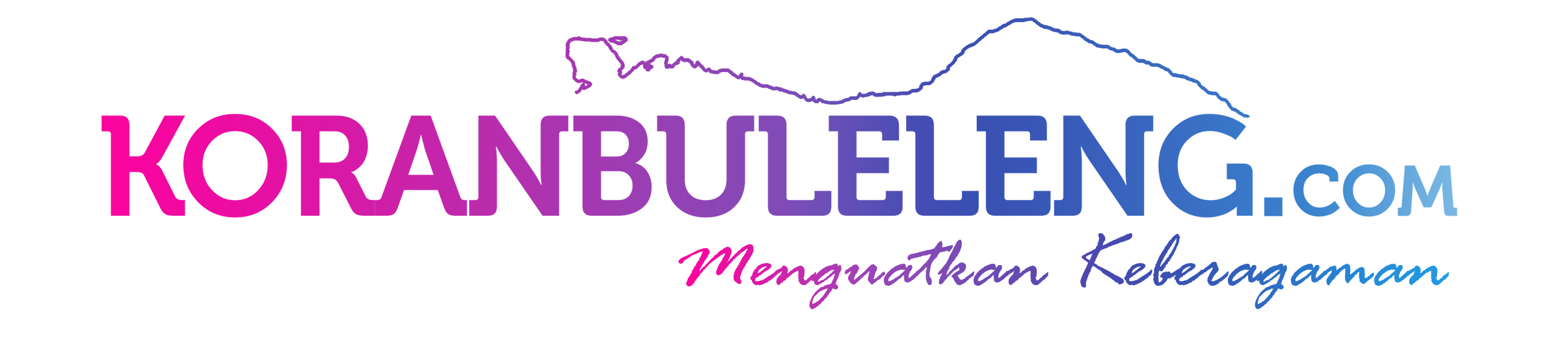Salah satu obyek wisata swafoto di Desa Wanagiri yang sampai kini belum beroperasi karena Pandemi COVID-19 | FOTO : YOGA SARIADA|
Para ahli pariwisata menyoroti kemajuan yang sangat cepat di satu pulau kecil yang hanya disebut “titik” oleh Muguel Covarrubias (Island of Bali), sekaligus meramalkan Bali akan rusak olehnya. Namun kapitalis tetap mengeruk Bali dengan kekuatan modal dan jaringan. Cita-cita pariwisata milik warga desa dengan modal nonkapitalis tidak pernah sanggup menandingi modal besar. Pariwisata Bali yang ada dalam mulut kaum kapitalis mengendalikan dan otomatis membunuh ide-ide pariwisata berbasis desa. Dalam hal ini modal menjadi senjata ampuh. Pemenang sudah pasti: kapitalis.

Disrupsi 4.0 dalam dunia pariwisata setidaknya mengubah kondisi mapan yang dikendalikan oleh kaum pemodal raksasa dengan munculnya aplikasi-aplikasi penjualan hotel, paket tour, transportasi, hingga kuliner. Teknologi yang digandeng oleh revolusi digital yang terbuka dan massal-global berpihak kepada siapapun tanpa kecuali, asal mampu menggunakan untuk suatu tujuan.
Makanya “menu” pelancongan yang sebelumnya puluhan tahun dikubur oleh kuasa modal dan dikendalikan dengan sangat baik untuk selanjutnya membunuhnya, mulai bermunculan. Hal ini menggerogoti pandangan elitis pariwisata Bali. Peralihan tengah terjadi, dari hotel berbintang ke “hotel” yang dikelola secara amatir milik warga desa; dari ikon-ikon pariwisata konservasi alam liar seperti Kebun Binatang di Bali ke “hutan desa” yang tetap lestari oleh sikap hidup yang dilandasi prinsip tri hita karana: palemahan.
Wisatawan tidak lagi dikendalikan ruang geraknya oleh peta elit yang hanya ada di lobi hotel berbintang “1000”. Wisatawan bergerak sendiri dimana mereka ingin, jauh di pedesaan Bali, pusat-pusat budaya dan ekonomi biru dan ritual-ritual kuno, dengan panduan Google Map. Mereka tidak lagi renang di kolam dengan klorin. Tetapi kini menemukan eksotisme Bali yang masih ada dalam visi modernisme barat, sebelumnya dikubur karena mungkin memiliki potensi mengancam narasi-narasi pariwisata kapitalis di tanah Balidwipa.
Sejalan dengan sumbangan Revolusi 4.0 yang sedemikian hebat, setiap individu menikmati berkah dengan gawai di tangan maka banyak hal bisa dilakukan, dari bikin status aneh di Facebook, menyiarkan kecelakaan yang pas ditemukan di jalan, hingga bikin video. Semua aktivitas yang sebelumnya diklaim politik ekonomi dengan label “profesional” kini rontok. Siapa saja bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya “tabu” professional dan sengaja membangun dua label sosial yang satu sama lain bertolak belakang: professional dan amatir. Teknologi gawai yang tersambung jaringan itu memberi semua kemudahan.

Tidak hanya ruang dan teknik produksi tetapi juga ruang dan jaringan mengumbar syahwat narsis. Peralihan terjadi lagi, dari media yang dikendalikan kapitalisme kertas menuju kuasa wrganet. Hal ini diikuti oleh konsekunsi-konsekuensi ekonomi atau imbalan. Maka telah muncul makna baru profesionalisme. Tidak lagi terjaga oleh prinsip elitis dan esklusif, tetapi produk-produk yang “viral”. Inilah kekuatan sosial tidak terbatas yang memberi legitimasi hidup manusia.
Kembali ke soal pariwisata dan akan dikaitkan dengan sebuah gagasan dalam buku Bali Tempo Dulu, memuat tulisan-tulisan orang barat mengenai pengalaman hidup di Bali, semasa penjajahan hingga menjelang berakhir. Satu tulisan mengenai perubahan pesat desa karena pariwisata yang dibangun dan dikelola di desa ini, oleh orang setempat. Mirip dengan gagasan desa wisata. Tulisan ini mengalihkan pandangan dari pariwisata di suatu kawasan “terlarang” seperti Ubud, Sanur, Kuta, dll. ke sebuah lokal yakni desa Memeling.
Gagasan dalam buku itu ternyata benar-benar jadi kenyataan berkat dukungan teknologi digital Revolusi Industri Generasi ke-4. Salah satu fitur dalam setiap gawai adalah kamera dan video yang telah menggoda warganet untuk selalu menggunakannya. Berfoto, bikin video, swafoto telah menjadi nafsu baru. Media sosial telah menyediakan ruang untuk ajang mempertontonkan diri warganet. Hal ini diiringi oleh nafsu lain, yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni mendapat perhatian (like dan komentar). Salah satu caranya adalah seting atau tempat berfoto. Maka jurang atau tebing yang mengerikan pun mulai jadi pilihan.
Hal itu lalu memantik ide kreatif untuk membangun apa yang dikenal dengan tempat selfi atau wisata swafoto, yang dikerjakan oleh perorangan, dengan modal sendiri yang seadanya. Biasanya menggunakan tanah milik sendiri yang mungkin letaknya strategis dan memang indah, dilatari hutan, sawah, pantai atau gunung. Ini menjadi objek wisata baru. Orang datang untuk berfoto dan makan minum sekadarnya saja.
Dalam waktu singkat sebuah tempat selfy viral dan untuk beberapa hari ke depan, dibanjiri pengunjung. Wisata ini hanya mengandalkan pemasukan dari tiket saja dan itupun sangat murah. Promosi tidak perlu dilakukan karena setiap warganet yang berkunjung sudah pasti akan mengunggah foto-foto dan videonya.
Itu semua promo gratis dan efek positifnya nggak tanggung-tanggung. Setiap foto yang diunggah selalu mengundang pertanyaan warganet, dimana tempat ini yang sama artinya dengan harus pergi ke sana agar tidak kalah gaya di medsos!
Sebuah wisata swafoto biasanya memiliki ikon yang sangat kuat, dipayungi oleh pemanfaatan potensi yang sudah ada, terutama karena keterbatasan modal. Karena itu, sungai bisa disulap jadi taman air yang keren. Sawah juga demikian, dipandang sebagai taman yang indah. Foto-foto air terjun berada di lokasi yang ekstrem kini menghiasi ruang media sosial. Ada pula bendungan atau empelan milik subak disulap jadi kolam renang. Jalan-jalan di kebun kopi yang hijau pun terasa sangat menggoda.
Fasilitas untuk mendukung potensi alam yang sudah ada dalam perkara wisata swafoto sepertinya sudah “paten” dan terstandar. Pasti ada kata-kata dan simbol cinta seperti pintu berbentuk hati dengan sedikit pemanis dari bunga plastik. Romantisme cinta warganet dengan segala kehangatan kasih dan cinta diwujudkan menjadi sebum kedis atau sarang burung yang dibuat dari ranting kayu.
Warganet berfose di dalam sarang burung ini. Ada pula yang lain, terkait dengan masa kanak-kanak, yakni ayunan tinggi yang tidak mau disebut dengan kata lokal tetapi menggunakan bahasa Inggris, swing. Ada pula koridor dan latar belakang foto.
Setahun atau tiga tahun setelah sebuah objek wisata swafoto dioperasikan, dibangun dengan modal ala kadarnya, mungkin para pengunjung sudah cukup datang sekali karena pasti itu lagi itu lagi, maka seperti siklus ekologi sarang burung di alam bebas, menjadi nasib yang menimpa objek ini.
Sarang burung itu pun lapuk karena tidak ada biaya untuk merenovasi atau mengganti dengan yang baru, juga karena hal yang masuk akal, tidak ada pemasukan mengingat pengunjung datang hanya sekali. Demikian juga ayunan tidak lagi bergerak. Mungkin pula talinya semakin membahayakan karena rapuh. Taman-taman meranggas di tepi koridor. Kata-kata dan warna di back dropt memudar.
Memang pada akhirnya, lihat saja sederetan wisata sarang burung di kawasan Wanagiri (Sukasada, Buleleng), benar-benar seperti nasib sarang burung yang sebenarnya. Setelah anak-anak burung siap terbang, maka sarang ini akan ditinggal. Demikianlah nasib objek wisata selfy. Disrupsi pun sebuah peluang besar tetapi ini jauh dari cukup. Wisata sarang burung mungkin tetap perlu modal yang memadai, pengelolaan, dan inovasi. (*)
Esai pariwisata ini ditulis : Dr. I Wayan Artika, S.Pd., .Hum. (Dosen Undiksha, Pegiat Gerakan Literasi Akar Rumput pada Komunitas Desa Belajar Bali, Kontributor koranbuleleng.com)