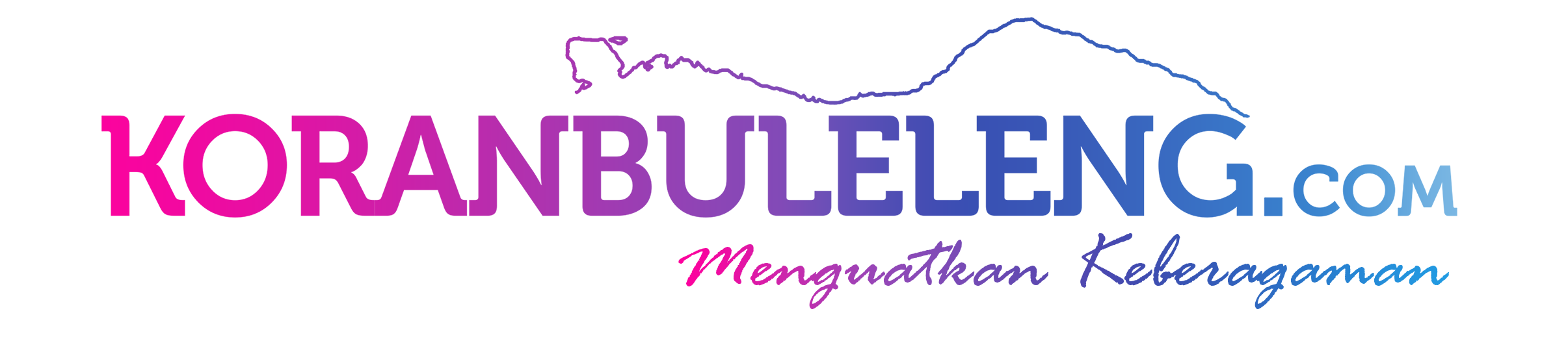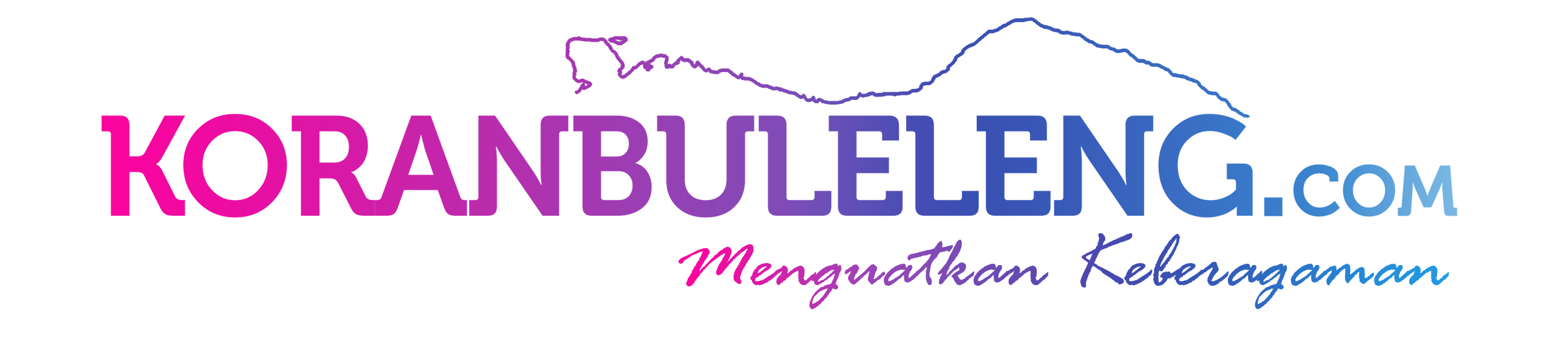Dari segi jurnalistik klasik, esai ini salah karena menulis mengenai peristiwa yang sudah lewat. Pasti para redaktur mencibir, “basi”! Namun demikian, esai ini baik-baik saja ala jurnalisme era disrupsi. Segala tatanan dipertanyakan dan “dihancurkan”.
Pada era ini tampak pemikiran besar Derida soal dekonstruksi menjadi aksi dan tidak selama sebelumnya, terinkubasi dalam wacana-wacana sosial, dalam lembaran risalah atau stadium jenderal di auditorium universitas.

Hari guru baru saja lewat dan sampai malam ini (25 November) media sosial masih ramai oleh semacam perhelatan sosial perayaan. Berbagai foto guru berseragam PGRI diunggah. Kata-kata indah pujian juga bermunculan. Sososk guru hadir dalam romantisme besar,
Jargon-jargon berkumandang bersama himne penuh puji. Mengenang jasa para guru bagi mereka yang sukses. Esai-esai normatif tentang empati terhadap sosok Omar Bakri, seorang guru bersepeda ontel dan tas kulit buaya-nya. Dan, tentu masih disematkannya sasanti “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” sebagaimana Orde Baru mengkonstruksi sosok guru Indonesia yang miskin dan sebagai anomali sosial: bahwa profesi guru tidak ada kaitan dengan kesejahteraan. Seakan guru tidak boleh kaya, seperti profesi lain.
Nah perubahan paradigma ekonomi telah menjadi antitesis guru miskin ala Iwan Fals, dengan tidak lagi himne sebagaimana proyek politik pendidikan masa Presiden Soeharto, yang sukses dengan SD Inpres, membangun tiga kompleks gedung sekolah dasar di sebuah desa mes atau rumah guru dan kepala sekolah, dengan jumlah penduduk tidak sampai 1000 jiwa di suatu desa.
Guru-guru akhir ini beda! Mereka sama sekali tidak merasa mengabdi menjadi tenaga pendidik. Mereka adalah kaum profesional. Guru adalah pekerjaan. Guru bukan para pengabdi bangsa. Tujuan mereka jadi guru bukan untuk mendapat predikat “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” atau dikagumi karena pengabdiannya tetapi menjadi guru untuk mendapat gaji yang layak. Guru bukan panggilan jiwa. Guru merupakan panggilan karier. Konsekuensinya adalah mereka menuntut upah yang layak.

Maka, wajah guru pada Hari Guru Nasional di media sosial sejalan dengan realitas. Guru-guru adalah insan muda yang dinamis. Mereka penuh rasa bangga dan percaya diri. Mereka ceria. Mereka menerima buket bunga berpita dan diselipi kartu ucapan, walau sedikit berkurang karena pandemi.
Maka ihwal ucapan itu semua yang datang dari para siswa, adalah sebuah keintiman. Hubungan siswa dengan guru bukan hubungan akademik instruksional tetapi hubungan keintiman jiwa atau hubungan yang terjadi secara alamiah dalam pola parenting atau pengasuhan sebagaimana hubungan guru dan murid dalam tradisi pendidikan upanisad. Inilah yang terjadi pada mahaguru hebat yang mengasuh Pandawa dan Korawa. Walaupun para mahaguru termulia dan terhormat itu mendapat satu kenyataan yang bertolak belakang.
Guru diterima siswanya bukan karena kehebatan guru itu secara akademik tetapi karena guru ini dapat merebut hati para siswa. Jadi hubungan guru dan murid masih pada tataran jiwa yang diliputi oleh variabel-variabel emosional. Di sekolah, anak-anak dari berbagai keluarga menemukan sosok orang dewasa lain dengan orang tua di rumah dan pada kasus ekstrem, dapat menggantikannya sehingga menjadi motivasi untuk datang ke sekolah. Hubungan ini pertama mengisi siswa atau hal yang fundamental dalam tradisi belajar di sekolah. Jadi, bukan hubungan akademik yang baru akan terjadi setelah hubungan hati nurani (jiwa) terjalin. Ubungan inilah yang dialami oleh Totto-Chan, Gadis Cilik di Jendela di sekolah gerbong keretanya, Tomoe Gakuen yang dikepalai oleh Kobayashi.
Memang ada banyak guru di sekolah-sekolah. Apakah semua guru mampu menjalankan peranan emosionalisme atau parentingnya? Tidak! Namun secara alamiah di suatu sekolah akan hadir sosok guru yang mengasuh. Sisanya adalah guru yang mengajar. Guru-guru yang mengasuh inilah yang menjadi daya tarik bagi siswa untuk betah ke sekolah selama bertahun-tahun. Mereka mengonvensasi guru-guru yang hanya suka mengajar dan memandang remeh pengasuhan atau parentingisme.
Guru-guru yang mengasuh ini membangun jalinan jiwa yang kuat antara sekolah dan siswa. Mereka kelak menjadi legenda yang akan selalu dikenang. Nah jika ada ucapan memuliakan guru-guru di media sosial hari kemarin ketika dirayakan sebagai Hari Guru Nasional, itu bukanlah untuk semua guru. Itu hanyalah untuk segelintir guru yang mengasuh atau guru-guru yang menjalankan laku parenting yang iklas sepanjang menjalani tugasnya di sekolah.
Bunga dengan pita cantik dan kartu ucapan dan mungkin atau setangkup tart adalah ekspresi jalinan jiwa khusus kepada guru sang pengasuh. Kondisi ini hanya dapat dihayati oleh siswa dan oleh guru-guru yang melakoninya. Ungkapan itu adalah hanya dipersembahkan bagi guru yang terpilih yang kelak tumbuh jadi legenda di dalam ruang jiwa para siswa baik yang sukses menjadi bupati atau walikota atau yang mengabdi jadi bendesa adat didesanyayang sangat sulit berubah, sekalipun di era disrupsi ini.
Jika lantas kembali dan lagi muncul kata-kata yang pada intinya menyatakan bahwa guru bukan orang hebat tetapi banyak orang hebat lahir dari guru tentu hal ini bukan omong kosong. Ini ada benarnya. Harus diakui sebagai omong kosong memang jika dikaitkan dengan laku para guru yang memilih hanya mengajar. Ungkapan ini adalah sebuah ode untuk para guru yang mengasuh, mereka yang menjadikan parentingisme sebagai cara berjalan di jalur profesi guru.
Guru parenting adalah guru yang melihat hubungan instruksional sebagai hubungan jiwa-jiwa dan bukan hubungan-hubungan fisik yang mekanik. Jiwa-jiwa itu dinamis karena selalu tumbuh dalam hidup. Maka capain tertinggi pendidikan parenting atau pendidikan yang mengasuh adalah terbinannya karakter anak didik. Secara ekstrem dikatakan bahwa akhir pendidikan adalah karakter.
Esai ini bermaksud mengingatkan kembali guru-guru yang berada di era disrupsi, jika peran pengasuhan atau parenting itu masih harus dikemukakan, maka melihat guru sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal fisik administratif tentu menjadi sikap yang sangat dangkal dan dekaden. Pada aspek pengasuhan atau parenting inilah fungsi guru yang nyata dan hadir tidak tergantikan.
Ketidakpercayaan siswa kepada PJJ atau distance learning atau belajar moda daring, dan yang lebih buruk lagi lewat WAG sebagaimana dilazimkan selama pandemi, karena moda dengan berbagai learning management system-nya (LMS) ini tidak dapat menghadirkan subjek-subjek hebat yang memerankan pengasuhan dan parenting itu. Materi boleh disalurkan lewat jaringan digital. Tetapi hubungan dan tindakan pengasuhan tidak dapat disalurkan lewat jaringan internet. Karena itu, variabel pertama pendidikan adalah pengasuhan atau parenting. Setelah ini terjadi barulah pendidikan menjadi belajar. Belajar yang kognitif adalah tahapan selanjutnya dari proses pendidikan.
Namun yang terjadi selama ini, ketika pendidikan nasional dikembangkan di bawah ideologi pembangunan, belajar yang sarat dengan urusan kognitif dinomorsatukan dan mengabaikan parenting atau pendidikan yang mengasuh. (*)
Penulis : Dr. I Wayan Artika, S.Pd., M.Hum. (Dosen Undiksha, Pegiat Gerakan Literasi Akar Rumput pada Komunitas Desa Belajar Bali)