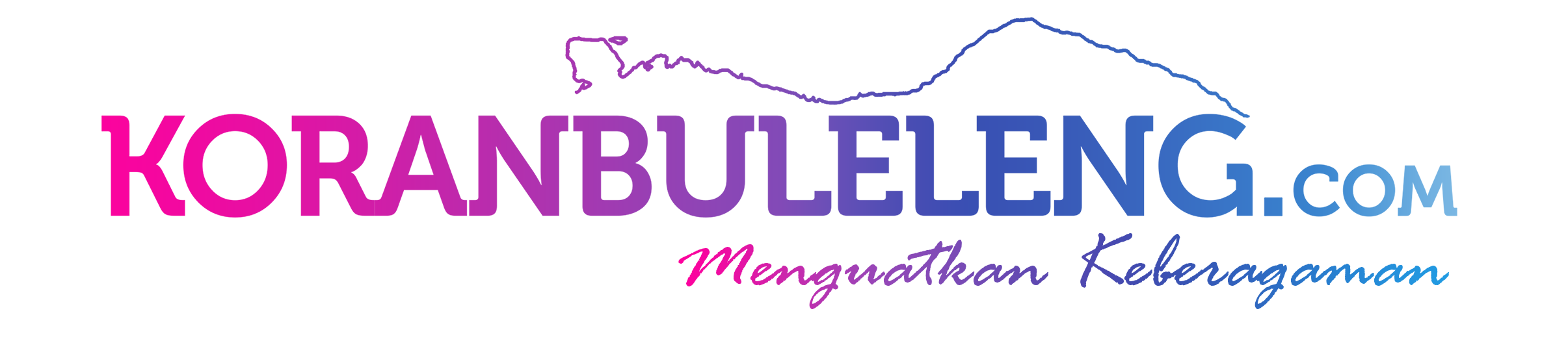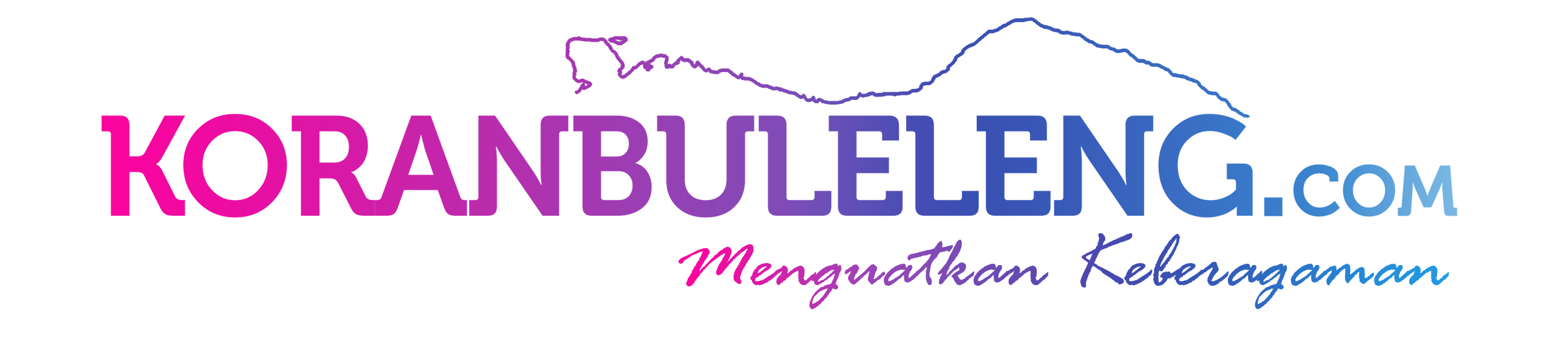Jauh sebelum penjajahan dan masa kemerdekaan yang melahirkan negara-negara baru, kota adalah pusat kerajaan yang menonjolkan aktivitas budaya, seperti penobatan raja, perayaan kematian seorang selir terkasih, nangkluk merana, upacara di pura, pertunjukan, yang adalah puri-puri kediaman raja dan keluarganya.
Kelak puri disulap menjadi ibu kota kabupaten atau provinsi modern. Usia sebuah kota ditarik jauh ke masa lalu sehingga bisa mencapai hitungan abad. Padahal kota-kota itu mengemban fungsi pemerintahan modern belum genap 80 tahun. Seakan setiap kota berlomba untuk menjadi tua. Di tengah kota yang dulu kerajaan, dibangun fasilitas yang ditiru dari penjajahan, seperti bank, sekolah, kantor administrasi, pasar modern, toko-toko, jaringan komunikasi, gedung kesenian, rumah sakit, penjara, terminal, jaringan listrik dn air bersih, pengolahan sampah, alun-alun, taman makam pahlawan kusuma bangsa, dan lain-lain.

Satu warisan penjajahan yang masih kuat di masa postcolonial adalah dikotomi desa/dusun dan kota. Paradigma ini membangun persepsi orang desa terhadap kota. Desa yang sebelumnya satu-satunya ruang sosial dan ekonomi tiba-tiba dilabeli dengan berbagai predikat keterbelakangan. Sebutan orang desa atau makanan desa misalnya, mengandung makna rendah. Sebaliknya, kota adalah identitas baru yang berkonotasi modern. Paradigma dikotomik desa lawan kota yang sedemikian adanya itu lalu menjadi pintu urbanisasi: perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Definisi ini menghiasi buku pelajaran sekolah dan soal-soal pilihan ganda, menjadi hafalan indah para siswa di masa silam; mengkonstruksi bayangan tentang kota yang penuh impian.
Urbanisasi mulai mereda ketika lahan semakin berkurang di kota, ketika transportasi berkembang lebih baik, ketika fasilitas-fasilitas baru merambah desa-desa, ketika sekolah-sekolah menengah menyebar hingga ke pelosok kecamatan. Itu semua merupakan senja kala urbanisasi, lebih-lebih ketika fasilitas pariwisata seperti hotel mewah justru dibangun di pelosok-pelosok kebun kopi di atas pegunungan atau di pantai-pantai yang terpencil, sebelumnya tidak terjamah, ketika wisatawan berkeliling desa-desa; memicu tumbuhnya desa-desa wisata.
Dengan paradigma yang telah diuraikan di atas, esai ini bermaksud mendiskusikan sebuah peristiwa desa yang diberi nama Festival Dusun yang diprakarsai oleh budayawan Wayan Udiana yang lebih populer dengan nama Nanoq Da Kansas. Perspektif bahwa ia adalah pemikir sosial yang mengambil habitus di ruang-ruang teks (karya) dan panggung (lokakarya, pertunjukan, dan lomba-lomba); maka migrasi habitus sedang berlangsung, dari ruang teks (kertas atau digital) ke ruang fisik atau organik (desa/Dusun Moding). Namun demikian, ruang teks masih terasa kuat ketika Wayan Udiana menyebut Dusun Moding dengan Dusun Senja yang sudah sangat terkenal di media sosial.
Ada pemikiran penting yang dapat dibaca untuk memahami migrasi ruang teks/karya ke ruang organik, yakni tulisan singkat di akun FB-nya (16/12/2021):

Rasa Kemanusiaan bukan soal seberapa hebat kamu menulis manusia dalam puisimu, novelmu, bukumu. Rasa Kemanusiaan adalah soal perilaku dan tindakan nyata dirimu kepada kehidupan di tempatmu sedang berada, wahai Nanoq da Kansas.
“Perilaku” dan “tindakan nyata” dalam kutipan tersebut adalah terminologi yang dioposisikan dengan puisi, novel, buku. Bagi dirinya, kertas atau digital sudah tidak cukup lagi sebagai habitus. Secara moderat, Wayan Udiana tengah berpikir soal keseimbangan dua ruang. Namun secara ekstrem ia sedang mempertanyakan kembali ruang-ruang kertas, digital, panggung organik atau virtual yang selama ini digelutinya. Sikap ini dapat dilihat kembali pada bentang sejarah filsafat seni dan berbagai gerakan sosial yang pernah ada: pertarungan antara seni untuk seni atau seni terlibat. Seni terlibat bukan semata seni terapan tetapi seni untuk mencapai tujuan sosial, seperti pembebasan kaum budak, sosialisme, peralihan penguasaan alat-alat produksi dari tangan kelas pemilik modal. Keemasan seni terlibat dicatat pada periode sejarah 1950-1965 ketika partai politik membangun mesin-mesin kebudayaan sebagai organ ideologi partai untuk mencapai kemenangan atau tujuan politik. Di tangan LEKRA misalnya, paham realisme sosialisme menjadi sangat nyata.
Fesitval Dusun (20 sampai 22 Desember 2021, di “Dusun Senja”, Banjar Moding Kaja, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana), tidak jauh dari aliran pemikiran realisme sosialis karena kegiatan ini meretas ruang-ruang teks kertas atau digital serta ruang-ruang formal; beralih ke desa dan menjadi bagian dari kehidupan warganya.
Esai ini memang tidak diarahkan untuk membahasas sikap, pemikiran Wayan Udiana dengan Festival Dusun-nya dari perspektif realisme sosialis, yang sejatinya sangat menarik ketika menghidupkan seni di desa-desa, yang telanjur dipahami sebagai ruang-ruang sosial yang antipuisi, antinovel, dan lain-lain. Esai ini berangkat dari gagasan ketika urbanisasi telah gagal dan persepsi yang menyatakan bahwa desa adalah wilayah terbelakang, masih berada dalam pikiran.
Wayan Udiana kembali kepada desa itu dan memfasilitasi para peserta dan masyarakat dengan suatu peristiwa bersama bahwa sudah waktunya memahami desa secara terhormat dan bebas dari sikap rendah diri. Desa-desa harus membangun dirinya sendiri dengan ideologi pembangunan dalam arti yang sangat luas dan holistik untuk mempertanyakan kembali, satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan desa, yakni ekonomi, seperti contoh adanya BUMDES. Desa juga harus dibangun seperti program Festival Dusun. Infrastruktur desa, jalan, gang, pura, makam, lapangan, vegetasi, subak, sungai, areal perbatasan hutan, burung, mamalia, ular, kadal, serangga, dan lain-lain harus terjaga. Sikap ini akan menjadikan desa dalam kondisi yang tertata. Pada umumnya, wajah desa masih terbengkalai. Seakan sampah plastik sah berserakan di desa. Seolah taman-taman dan monumen hanya milik warga kota. Jalan-jalan yang bersih atau perupustakaan yang bergaya kafe juga layak dinikmati warga desa.
Festival Dusun memiliki makna sangat penting dari dekonstruksi persepsi yang merendakan desa. Hal ini menjadi sangat masuk akal ketika urbanisasi telah menjadi masa lalu dan kota sudah berhenti tumbuh. Kota tidak lagi memberi harapan. Desalah yang menggantikan harapan itu. Di tangan beberapa kepala desa yang hebat, desanya dibangun dengan baik dan sukses. Desanya adalah halaman atau wilayah yang paling nyata dan paling terjangkau dari Republik Indonesia. Indonesia itu ya desa itu.
Jauh di tingkat pusat muncul pemikiran yang telah dilaksanakan, Indonesia dibangun dari pinggiran dan desa-desa menerima dana dalam jumlah besar namun pemerintah desa dan SDM-nya miskin program karena tidak cukup mampu memahami pembangunan desa era Presiden Joko Widodo. Dana yang banyak itu tidak terkelola dengan baik. Akhirnya digunakan untuk melulu pembangunan fisik. Gang yang tahun lalu disemen tahun ini dipasangi paving block. Tidak terbayang warga desa mendapat layanan pembangunan dana desa yang menyasar program mental, seperti literasi, bernalar, berapresiasi seni, konservasi, kreativitas, dan lain-lain. Dana desa dan pembangunan desa sudah waktunya diarahkan untuk membiayai proyek-proyek pembelajaran seumur hidup bagi warga desa.
Wayan Udiana dengan Festival Dusun-nya telah mengajak kembali ke desa dengan proyek kebudayaan dimana warga Desa Moding sebagai subjek berkolaborasi dengan para tamu yang terlibat. Ia juga seperti tengah menyuarakan sindirian kepada aparat desa yang masih tidak cerdas mengelola pembangunan desa, yang hanya berkutat dengan semen dan paving blok. (*)
Penulis : Dr. I Wayan Artika, S.Pd., M.Hum. (Dosen Undiksha, Pegiat Gerakan Literasi Akar Rumput pada Komunitas Desa Belajar Bali)