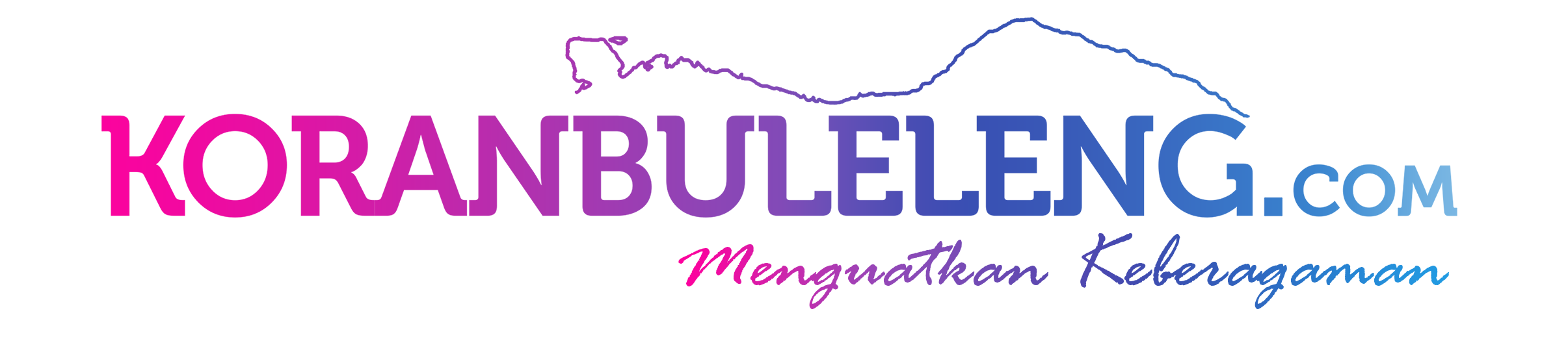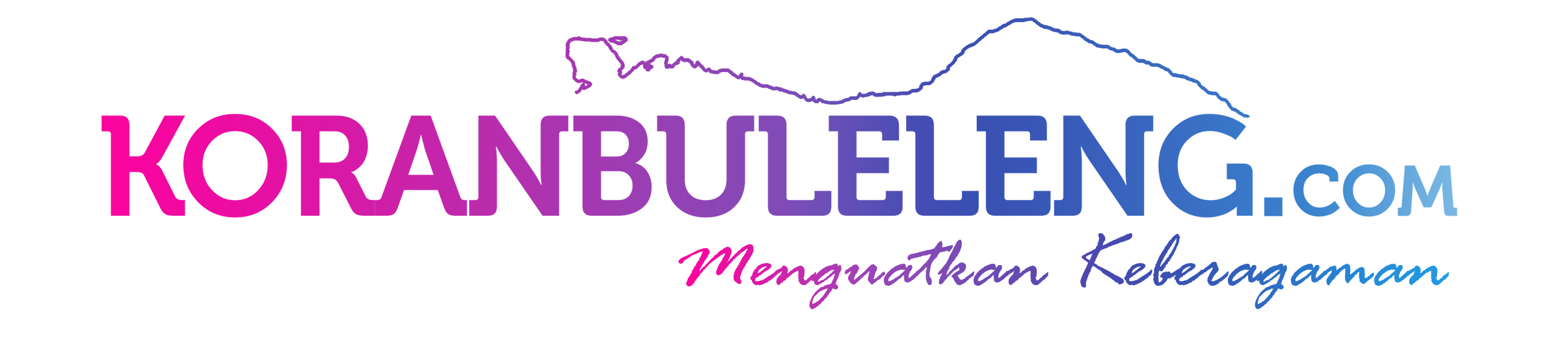Pagi sedikit cerah kala itu. Terlihat wajah Gunung Batukaru begitu dekat dengan Desa Batungsel.
Pemandangan beda di sebuah SD tertua di Kecamatan Pupuan, SDN 1 Batungsel. SD ini berdiri tahun 1943.

Sekolah ini juga merayakan bulan bahasa Bali, tepatnya dimulai 4 Februari 2023. Siapapun tahu kalau setiap bulan Februari (semenjak pemerintahan Gubernur Wayan Koster) seluruh desa adat wajib melaksanakan kegiatan bulan bahasa Bali, tapi dengan berbagai kegiatan yang itu-itu saja seperti lomba-lomba yang identik dengan bahasa dan sastra Bali.
Walaupun monoton dan tampaknya kurang inovatif apalagi dikaitkan dengan zaman milenial toh bulan bahasa Bali selalu dirayakan dengan meriah.
Kali ini perayaan bulan bahasa Bali di SDN 1 Batungsel bisa dikatakan berbeda dengan agenda-agenda yang itu-itu saja. Hal ini berkat kerja sama yang dijalin oleh kepala SDN 1 Batungsel, Santun Arini. Ia bekerja sama dengan Jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Ganesha dan di mediasi oleh Komunitas Desa Belajar Bali.
Program unggulan yang dibawa mahasiswa adalah pelatihan nyurat lontar. Pelatihan ini menarik sekali karena sangat jarang dilakukan sebab biayanya mahal. Pelatihan nyurat lontar ini menggunakan lontar asli yang sudah siap ditulisi dan dibeli hanya khusus ada di daerah Karangasem. Hal ini perlu dijelaskan karena masyarakat Bali pada umumnya apalagi siswa tidak tahu kalau lontar yang digunakan untuk nyurat aksara adalah melalui proses yang sangat panjang. Hal ini bisa dibaca di dalam berbagai pustaka kuno atau kajian-kajian filologi.

Di samping menggunakan lontar asli. kegiatan ini juga menggunakan pisau tulis yaitu pengrupak. Untuk ini mahasiswa mengumpulkan seluruh pengrupak yang wajib dimiliki oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Bali. Tentu saja kegiatan ini sangat menarik bagi siswa SD kelas 4 5 dan 6. Mereka diperkenalkan dengan cara menulis yang sama sekali baru, milik leluhur mereka sendiri.
Mereka memang mendapat pelajaran bahasa Bali termasuk aksara namun tradisi tulis asli tidak pernah diajarkan di kelas-kelas dan ini terjadi di seluruh Pulau Bali. Namun demikian, tradisi nyurat lontar yang asli memang muncul sesekali waktu ketika diadakan Pesta Kesenian Bali (PKB) misalnya. Pada saat Pesta Kesenian Bali ada lomba nyurat lontar dan demikian pula beberapa kampus di Bali rutin menyelenggarakan lomba nyurat lontar bagi siswa SMA dan sesederajat.
Kelas-kelas pelajaran bahasa Bali tidak pernah mengenalkan tradisi ini. Tentu alasannya adalah sulit mendapatkan lontar dan pengrupak. Rasanya lebih mudah mendapatkan tradisi digital dalam pelajaran bahasa Bali. Itulah mengapa kegiatan workshop surat lontar di SD 1 Batungsel sangat menarik perhatian siswa dan para guru serta masyarakat setempat.
Pelatihan nyurat lontar ini adalah suatu penyadaran bahwa selama ini pelajaran bahasa Bali di sekolah formal minus pengajaran atau pengenalan konteks kehidupan atau tradisi yang melahirkan menghidupkan bahasa dan aksara Bali itu sendiri. Memang bisa saja berapologi bahwa lontar sudah tidak diperlukan dalam tradisi keberaksaraan modern karena sudah ada teknologi digital yang lebih praktis.
Namun demikian, tradisi terkadang bukan berbicara persoalan nilai praktis semata atau relevansinya kepada kehidupan saat ini tetapi tradisi berkaitan dengan makna dan sebuah kedalaman penghayatan. Menghayati kehidupan dan taksu aksara Bali tentu harus kembali kepada rumah dan ruh tradisinya, yaitu skriptorium kuno tempat para penekun aksara bekerja di bawah kendali taksu aksara karena bagi orang Bali aksara itu adalah media dan bisa dihidupkan.
Ketika aksara Bali ditulis secara digital maka ini menjadi hal yang asing dan baru. Karena itu penghayatan makna dan ruhnya tidak didapat oleh para siswa. Inilah alasan mengapa menjadi sangat penting pengenalan tradisi yang menghidupkan bahasa dan aksara Bali serta karya sastranya; dimasuki oleh orang Bali, termasuk para siswa.
Kejutan yang tampak pada kegiatan nyurat Lontar di SD 1 Batungsel mengingatkan bahwa tradisi ini sedemikian jauh dan sudah hilang namun catatan khususnya adalah sebelum tradisi ini hilang karena digantikan oleh kertas dan aksara latin yang menguasai dunia karena aksara ini dikembangkan sebagai sebuah keberuntungan dengan teknologi tulis dan percetakan.
Kondisi yang menimpa masyarakat Bali sejak dahulu kala adalah mereka tidak pernah mengenal tradisi nyurat lontar secara massal dan itulah sebabnya mereka menjadi buta aksara massal. Tradisi nyurat lontar pun menjadi eksklusif. Jika alasan yang diajukan adalah karena mahalnya materi atau alat tulis seperti lontar dan pengrupak, maka ini pastinya kurang masuk akal. Pada masa lalu banyak pohon Lontar tumbuh di sepanjang garis pantai Bali Utara dari Gilimanuk hingga di ujung timur pulau di Karangasem.
Tentu bahan Lontar tersedia melimpah. Demikian pula halnya hampir di seluruh desa di Bali bermukim warga pande yang tidak hanya menempa baja menjadi keris dan tombak untuk berperang bagi wangsa ksatria tetapi juga warga pande bekerja untuk melayani kebutuhan peralatan rumah tangga.
Demikian pula halnya menghasilkan pengrupak untuk tradisi menulis lontar secara massal; bukanlah suatu halangan.
Tapi mengapa masyarakat Bali tidak memiliki alat-alat menulis lontar? Artinya, sangat jarang menemukan orang-orang yang terampil menulis lontar pada setiap rumah pada setiap desa di seluruh Bali, sebagaimana halnya orang-orang Cina atau Jepang yang terampil menuliskan aksara di atas kertas-kertas tradisi mereka dengan kuas dan tinta. Karena itu, orang Bali sejatinya adalah buta aksaranya sendiri.
Hal ini mungkin bisa temukan jawabannya pada klaim atas ilmu pengetahuan dan jalan masuk ke dalamnya yakni keberaksaraan atau melek aksara yang sengaja tidak dijalankan dalam peradaban Bali; justru sebaliknya dimiliki dan dikuasai atas satu klaim kelompok tertentu yang paling berhak. Maka jangan salahkan kalau orang Bali buta aksara dan sama sekali tidak mengenal tradisi dan teknologi nyurat lontar.
Lewat kegiatan bulan bahasa Bali di SD di kaki Gunung Batukaru sebelah barat ini ada satu refleksi penting betapa pelajaran bahasa Bali di sekolah harus bisa menyajikan tradisinya karena dengan mengenal tradisinya para siswa akan memetik makna yang mendalam dan menghormati aksara itu sendiri. Hanya tradisilah yang mampu menghidupkan dan menghadirkan aksara Bali dalam pembelajaran di sekolah. Pelajaran bahasa Bali harus mengenalkan aksara dalam tradisinya yang asli yaitu tradisi nyurat lontar dengan teknologi aslinya. Jika bersandar pada aksara Bali di dalam program-program komputer seperti Bali Simbar lantas mengapa orang Bali masih enggan mempelajari aksara Bali. Artinya kemudahan teknologi digital dan komputerisasi aksara tidak menjadi jaminan akan membebaskan masyarakat Bali dari buta aksara?
Workshop nyurat Lontar dengan menghadirkan tradisi aslinya ke hadapan anak-anak bisa dijadikan model bagaimana mereka begitu takjub kepada taksu yang menghidupkan aksara Bali. Catatan penting kegiatan ini tentu saja pelajaran bahasa Bali jangan mengalih dari tradisinya yang menyimpan taksu; ke tradisi baru yang hampa. Anak-anak SD kelas 4, 5, dan 6 yang diikutkan dalam program ini memiliki pengalaman baru memasuki tradisi aksara Bali dan mereka melakoninya walaupun hanya dalam beberapa jam.
Kelas ketika itu sungguh berbeda suasananya. Anak-anak dengan selembar Lontar di tangan kirinya dan pengerupak tajam berkilau di tangan kanannya, menggurat aksara demi aksara dengan rasa takjub dan kagum sepertinya mereka tampak sebagai para bocah penyalin lontar yang bekerja pada sebuah skriptorium. (*)
Penulis : Dr. I Wayan Artika (Akademisi Undiksha dan Penggiat Komunitas Desa Belajar Bali di Desa Batungsel)