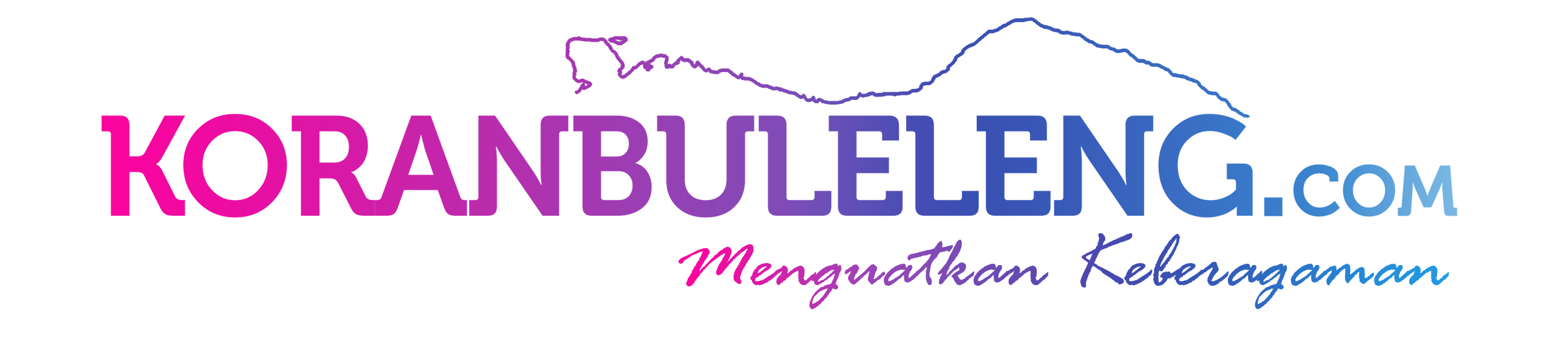Hamparan persawahan di Desa Batungsel, Tabanan menjadi ciri desa sebagai penampakan warisan leluhur warga desa setempat |FOTO : Wayan Artika |
Kontributor : Wayan Artika

Gawai menawarkan realitas atau dunia baru. Demikian pun sebagai keniscayaan bagi anak-anak di desa kaki Gunung Batukaru. Yang menjadi soal, dunia virtual ini menguasai kehidupan mereka. Yang lebih menakutkan, para orang tua tidak menganggap kuasa realitas virtual berfiranti gawai sebagai persoalan. Dan, tentu yang paling parah, orang tua tidak berkutik! Menyerah kepada massalisasi hegemoni realitas virtual pada anak-anak mereka.
Transformasi ekonomi rural agraris yang guyub ke ekonomi uang memicu orang tua bekerja dan bekerja untuk mengumpulkan uang agar dapat memenuhi keperluan hidup keluarga. Tidak ada waktu lagi untuk mengasuh anak-anak. Mereka ditinggalkan di rumah dan secara masif diasuh oleh gawai dengan berbagai konten yang belum tentu relevan. Dunia virtual berbagai konten yang ditemukan lewat media gawai, membuat jarak yang lebar di antaranya dengan realitas desa.
Desa Batungsel, sebuah desa yang paling dekat dengan lereng barat Gunung Batukaru, di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, sesungguhnya memiliki berbagai kekayaan narasi yang indah, jalan setapak lintasan para leluhur, sawah-sawah, hamparan kebun kopi, ratusan serangga, ikan-ikan di sungai Yeh Kelih, aneka burung, kumbang, lumut, paku-paku raksasa, batu-batu besar di lembah DAS sungai atau pangkung-pangkung, empelan, pohon-pohon besar, pura-pura peninggalan budaya megalitikum, aneka satwa liar yang berumah di alas tutupan Batukaru, titik-titik untuk menyaksikan matahari terbit dan terbenam, pancuran dari mata air jernih, dll. Namun demikian, semua potensi keindahan dan kekayaan lokal ini tiada berguna dalam pikiran anak-anak yang tersandera di dunia virtual.
Jika sebelum gawai menjadi kenyataan massal masif anak-anak desa, sekolah pernah ditengarai sebagai pencipta jarak, antara kurikulum dan realitas. Namun, hal ini masih memungkinkan untuk diretas karena realitas kurikulum dan realitas desa, sama-sama realitas fisika dan sosial. Tapi, kini perhatian kepada persoalan baru yakni realitas virtual. Jiwa, pikiran, dan penghayatan anak-anak benar-benar tergerus dan dialihkan ke dalam realitas virtual. Sepanjang hari mereka tidak bisa lepas dari gawai.

Jauh pada masa sebelum era massalisasi gawai, hari raya galungan seperti tahun ini misalnya, adalah saat ketika mereka menikmati hari raya yang indah dengan kemeriahan dan permainan di halaman-halaman rumah. Mereka menikmati air di sungai. Mereka pergi ke kebun-kebun kopi atau bermain di hamparan sawah dengan pematang yang meliuk-liuk. Mereka memiliki agenda-agenda “petualangan” di alam desa. Mereka dapat menghayati vegetasi dan arah angin atau pertanda hujan lebat, mendengarkan suara perjalanannya ketika tangkai-tangkai air menyentuh daun-daun hutan Gunung Batukaru.
Atau mereka memancing di sungai. Mencari kayu api. Berenang. Mencari capung. Memanen madu liar.
Tetapi ketika gawai menyeret anak-anak desa ini, dan demikian “nasib” hampir semua anak pada zaman Revolusi 4.0, ke dalam realitas virtual, maka mereka tidak lagi menghayati hidup di desa ini. Narasi-narasi harimau dan para hero tentang Gunung Batukaru yang hidup dan suci, tidak lagi mereka kenal. Bahkan, keterampilan “membaca” pohon yang muncul ketika senja cerah di lereng gunung ini, terlalu mustahil mereka lakukan. Demikian pula kisah bongkahan batu yang menyerupai perahu yang terdampar atau batu tapak kuda.
Realitas virtual telah menghapus kehadiran desa pada hidup anak-anak di desa ini. Namun demikian, orang dewasa memilih untuk menyerah. Berdamai dengan perubahan besar. Para orang tua memang tidak sepenuhnya terseret ke dalam realitas virtual karena mereka adalah hanya kaun migran digital. Tapi anak-anak mereka atau cucu-cucu adalah digital native. Yang mereka miliki bersama, di antara dua generasi: perbedaan realitas yang saling mendominasi: realitas fisika, sosial, pada satu pihak dan realitas virtual di pihak lain.
Karena perbedaan realitas ini, orang tua menjalani hidup tanpa anak-anak mereka. Anak-anak sibuk dengan gawai. Orang tua bekerja di kebun-kebun atau sawah tanpa kesempatan parenting. Pengetahuan yang didapat dari gawai oleh anak-anak desa ini adalah hal-hal yang aneh. Pengetahuan ini tidak berjejak dalam narasi-narasi desa.
Begitulah hebat dan sakti teknologi jaringan. Dongeng-dongeng desa ini telah dibunuh pula. Anak-anak sibuk dengan aktivitas “mabar” yang semakin gila.
Maka, dalam pengamatan satu minggu, selama hari raya galungan 2021 ini, tercatat keluhan-keluhan yang kelu para orang tua yang kalah. Mereka hidup di suatu geografi desa yang dipisahkan oleh dua realitas yang bertolak belakang. Maka dengan kesadaran bahwa realitas virtual tersebut tidak selalu relevan dengan anak-anak, sebagaimana sesungguhnya tidak siap diterima oleh orang tua, maka, lembaga pemerintahan desa mesti ambil peran, dengan mengeluarkan kebijakan lokal untuk mengembalikan anak-anak ke realitas desa.
Memang sangat jarang pemerintahan desa yang sanggup mengatasi persoalan ini. Anak-anak hanya diperhatikan segi pendidikannya saja. Lembaga kesehatan kecamatan mungkin hanya melihat anak dari segi medis. Tapi pertarungan-pertarungan mental mereka memasuki kehidupan yang terhegemoni oleh habitus realitas virtual, sama sekali diabaikan.
Ketika secara perseorangan orang tua mengeluh dan bingung atau telah menderita putus asa dalam menghadapi kuasa realitas virtual, maka “perlawanan” atau negosiasi harus dilakukan secara melembaga. Anak-anak desa harus sedapatnya dikembalikan kepada realitas geografi dan sosial budaya desa.
Realitas inilah yang menjadi fokus hidup dan kemudian dibina untuk mengubah realitas geografi ini menjadi realitas virtual, agar mereka tidak menjadi pecundang. Anak-anak desa harus dibantu dan disadarkan bahwa cara mereka memahami realitas virtual sangat keliru. Mereka hanyalah “budak”. Kondisi yang buruk ini harus diubah agar anak-anak desa selamat.
Mereka menggunakan teknologi digital dengan firanti massal gawai tanpa pernah sebelumnya mendapat “pengarahan” atau “pembinaan”, bagaimana seharusnya sehingga mendapat manfaat. Anak-anak begitu mudah menggunakan teknologi ini. Mereka tidak memiliki prinsip-prinsip. Realitas virtual hanya dinikmati untuk candaan, hiburan yang berlebihan dan harus dibeli dengan mahal. Artinya, anak-anak ini tidak mendapat manfaat rohani dan moral apapun dari realitas virtual yang menyandera mereka.
Maka tugas lembaga desa adalah membantu anak-anak agar tidak tersandera di tengah-tengah realitas virtual. Mereka harus dilatih menggunakan gawai. Mereka harus diawasi dengan keras. Hal ini harus menjadi gerakan sosial berbasis desa. Lembaga-lembaga desa tidak boleh membiarkan atau mengabaikan persoalan ini.
Liputan ini adalah pengalaman nyata dari sebuah desa yang ditulis dalam bentuk laporan interpretatif, bermaksud mengimbau aparat desa agar menyadari bahwa pada dunia anak-anak, persoalan Revolusi Industri Generasi ke-4 tidak lagi sebatas disrupsi tetapi menjadi ancaman serius kehidupan anak-anak. Mereka tidak lagi memiliki realitas geografi desa tempat mereka tinggal bersama keluarga tetapi tiada disadari betapa terancam kehidupan oleh realitas virtual yang menyandera, memperbudak, dan bikin gila! (*)