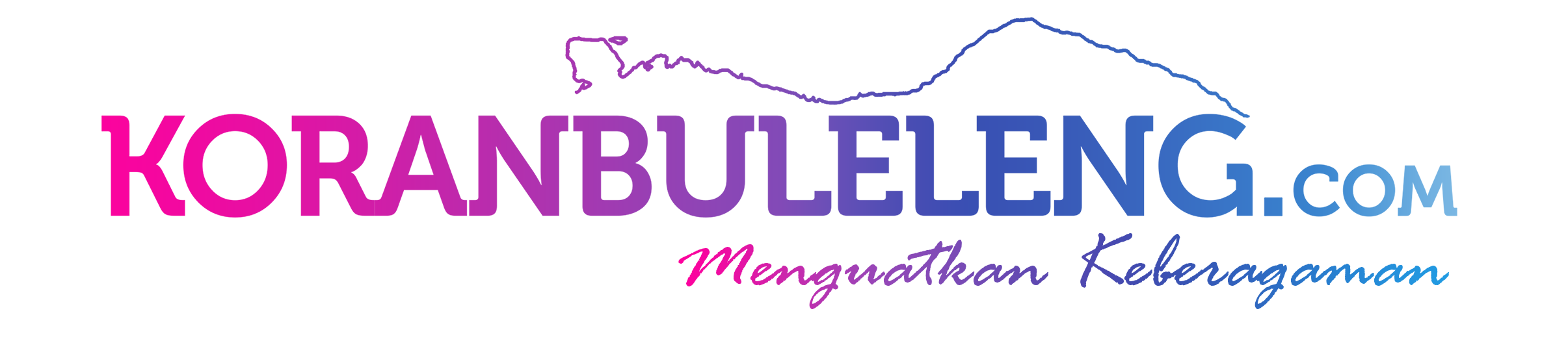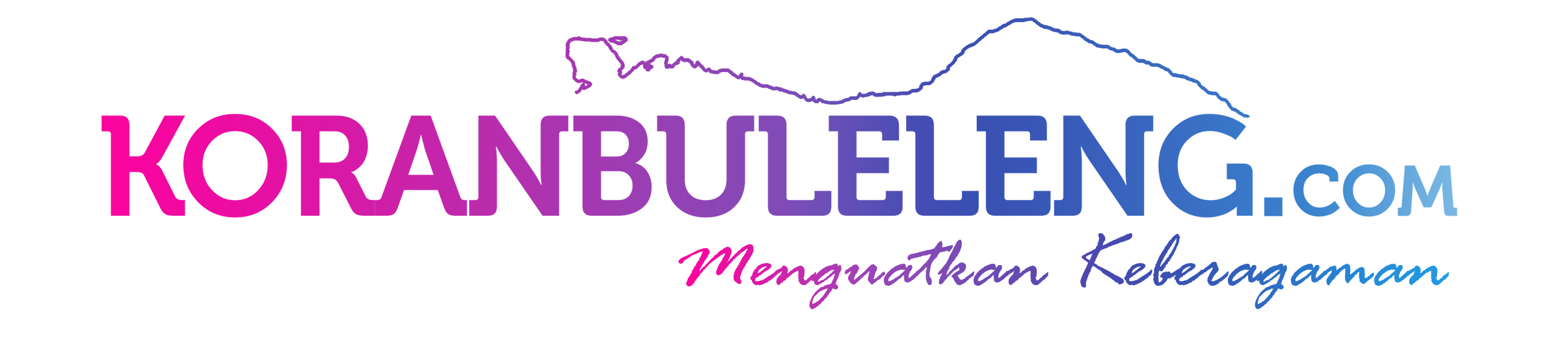Cerita, tulisan, catatan perjalanan, atau film-film dokumenter, apapun itu, mengenai Desa Tenganan, sungguh sangat menakjubkan. Para penulisnya rata-rata terbius oleh pesona desa ini. Mungkin karena teknologi tenun dobel ikatnya yang tetap lestari, perang pandan dalam upacara mekare-kare, atau hidup yang tidak hanya selaras irama alam tetapi juga memposisikan diri jauh di bawah keagungan dan kuasa alam itu sendiri.
Pandangan-pandangan dari luar memposisikan desa ini sebagai episentrum eksotisme yang sangat diagungkan dan diburu oleh kaum pelancong kolonial ketika Eropa diobrak-abrik oleh rasionalisme modernisasi setelah Revolusi Industri. Konstruksi pariwisata kolonial yang “menghidangkan Bali sebagai sorga terakhir” di Eropa adalah iklan dengan dampak luas, hingga memasuki beberapa dekade kemudian. Bali pun menjadi tanah impian tidak hanya bagi K’tut Tantri tetapi bagi bangsa-bangsa barat yang kehilangan masa lalu akibat Revolusi Industri dan Perang Dunia.


Di dalam Bali yang diiklankan seperti itulah Tenganan Pegringsingan terhidang. Tenganan hadir dengan sangat indah dan penuh romatika. Walaupun iklanisasi Bali di industri pariwisata dunia sedemikian rasional namun Miguel Covarrubis memandang Bali dengan lebih kritis. Pada akhir Island of Bali ia menulis pargaraf-paragraf kekhawatiran di masa depan bahwa Bali akan rusak oleh pariwisata. Mungkin benar, kelak, kekhawatiran itu nyata namun perlawanan untuk menolaknya, juga sangat kuat.
Ketika Bali diancam oleh berbagai peristiwa yang berpotensi menyurutkan aktivitas ekonomi pariwisata, seperti oleh teorirsme (Bom Bali) dan yang paling mutakhir adalah pandemi covid 19; justru orang Bali sendiri menyatakan diri bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa pariwisata. Karena itu, bicara Bali, desa, pantai, upacaranya, alamnya, tari dan drama-dramanya, pun arsitektur, atau warisan literasi di atas daun lontarnya; terasa hambar jika tidak mengaitkan dengan pariwisata.
Namun demikian, di Tenganan Pegringisngan sebuah anomali terjadi. Setidaknya inilah yang disajikan dengan kuat dalam seri dokumenter Ekspedisi Indonesia Biru. Film ini berhipotesis bahwa ekonomi pariwisata adalah ekonomi pembawa polutan bagi lingkungan dan budaya masyarakat, walaupun pernah dinyatakan sebagai industri tanpa asap; Tenganan bisa bertahan dan berdampingan dengan pariwisata dunia tanpa harus tergerus untuk lebur ke dalamnya. Rumusan yang diusung sebagai tesis dalam film ini menyatakan, bagi Desa Tenganan pariwisata adalah bonus. Tenganan memang tidak menutup diri dari kunjungan para tamu. Tenganan juga tidak merespons pariwisata secara berlebihan.
Masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan menjalani hidup seperti sedia kala. Mereka terbiasa dengan kehadiran orang asing. Tidak ada niat untuk mendirikan rumah makan, membangun hotel, memasang tarif masuk, tidak ada fasilitas-fasilitas baru. Bahkan, tidak ada usaha untuk melakukan apapun demi pariwisata. Orang luar memandang Tenganan sebagai destinasi penting sehingga patut dikunjungi. Tapi bagi orang Tenganan, tidak! Apapun yang mereka lakukan dalam basis-basis sosial, religius, dan lingkungan; semuanya untuk diri mereka.

Perspektif pariwisata memandang Desa Tenganan sebagai destinasi dengan banyak daya tarik. Tapi bagi warga desanya sendiri, desanya sama saja dengan desa-desa di sekitarnya. Mereka memiliki sejumlah pura dan bangunan di sepanjang halaman desa yang menyerupai jalan raya yang dikeraskan dengan batu-batu kali atau batu-batu gunung , memiliki upacara kematian, menyelenggarakan ritual sesuai dengan kalender, membangun rumah di atas denah yang telah disepakati di masa lalu, dan lain-lain.

Jarang sekali ada tulisan atau catatan yang mencoba mempertanyakan, mengapa Tenganan Pegringsingan menjadi desa yang berbeda dan satu-satunya di kawasan ini khususnya atau di Bali pada umumnya? Pertanyaan ini menarik mengingat Desa Tenganan bukanlah desa yang terpencil. Maka jika kondisi Tenganan hari ini dengan segala keunikan dari desa-desa tetangganya, tentu bukanlah terjadi karena faktor geografi tetapi karena mungkin desa ini membentengi diri dengan ideologi yang kuat, yang mungkin dapat dilihat representasinya pada tiga sisi bukit yang mengurungnya. Celah di pintu gerbang desa hanyalah akses untuk tidak menjadikan diri terisolasi dan bukan untuk mengalirkan perubahan ke dalam desa. Jika ini menjadi jalan masuk ke Tenganan yang dilalui oleh wisatawan mancanegara dan domestik, kahadiran mereka sama sekali tidak menggiurkan. Kehidupan yang biasa dan normal tetap berlangsung di desa ini. Karena itu, ritus-ritusnya tidak pernah mereka “jual” untuk dijadikan tontonan. Kawasan pantai Candi Dasa adalah kontras dengan Tenganan karena desa Bugbug memang menyambut pariwisata dengan kesadaran ekonomi.
Memandang pariwisata hanya bonus, sebagaimana ditonjolkan dalam Ekspedisi Indonesia Biru, sudah pasti kiranya, Tenganan hanya meminta sedikit saja dari pariwisata. Esai ini membahas yang sedikit itu, ketika mengunjungi desa ini di ujung pandemi (24/8/2022).
Jika terlalu yakin dengan gambaran desa ini yang dimuat di berbagai buku dan media sosial atau film-film dokumenter; tentu saja akan ada sedikit pertanyaan ketika berkunjung secara langsung. Karena itu, memang harus kembali kepada satu kesadaran bahwa warga desa ini tidak dalam rangka menyambut wisatawan. Tata ruang desa yang terdiri atas jalan lebar sebagai pusat orientasi komunalitas, dikeraskan dengan batu kali, tempat berbagai bangunan pura dan balai-balai yang panjang, ke sinilah setiap pintu rumah mengarah; tidak terpelihara sebagaimana sebuah taman. Secara umum wajah pekarangan desa ini seperti pada galibnya desa-desa yang warganya hidup sebagai petani, tukang bangunan, nelayan, atau undagi. Wisatawan harus siap dengan keadaan desa yang memang asli. Karena itu, cara memandang Tenganan dalam kondisi yang asli sebagai sebuah desa pada umumnya di Bali dengan sedikit kekhasannya, ketika mengunjunginya, mungkin harus diubah. Para wisatawan tidak cukup kalau hanya sebatas menyaksikan pemukiman desa, melintasi jalan besar dengan berbagai tipe bangunan dari kayu di tengah-tengannya, menyaksikan sisa tembok rumah kuno yang berdampingan dengan yang baru, menghadirkan rasa tidak lagi autentik; tetapi harus bisa masuk ke balik tembok lewat pintu-pintu kecil yang menghadap ke jalan desa. Di sinilah wisatawan dapat melihat Tenganan yang sejatinya. Mereka tengah mencoba untuk meraup berkah pariwisata. Rumah-rumah mereka adalah juga toko-toko barang kerajinan. Di sinilah para wanita menenun kain gringsing yang terkenal ke seluruh dunia. Di sinilah kaum laki-lakinya juga ikut membantu pekerjaan-pekerjaan perempuan. Rumah yang sangat kecil ukurannya juga menjadi bengkel-bengkel tenun.
Di dalam rumah-rumah dengan ukuran yang sama, yang tidak pernah bisa menambah jumlah warga yang tinggal di dalamnya, juga tanpa ada rumah baru di bangun di wilayah desa ini; warga desa tenganan sedang berjualan aneka rupa kerajinan yang diambil dari pasar seni di Gianayar, tekstil dengan teknologi dobel ikat, prasi, dan berbagai perlatan kecil seperti kotak tisu, alas makan dari ata.
Memang ada keramahan di dalam rumah-rumah itu, namun ada sedikit yang mengganjal, ekspresi-ekspresi dan bahasa tubuh yang memaksa para wisatawan untuk membeli apa saja yang mereka jual. Mungkin ini sebagai dampak pandemi, ketika Tenganan ditutup selama dua tahun.(*)
Penulis : Dr. I Wayan Artika (Akademisi Undiksha)