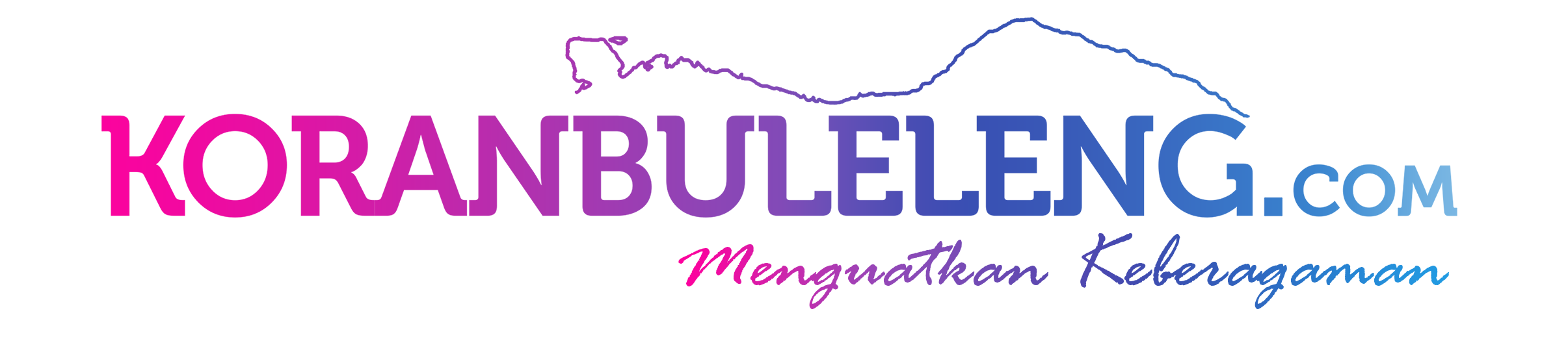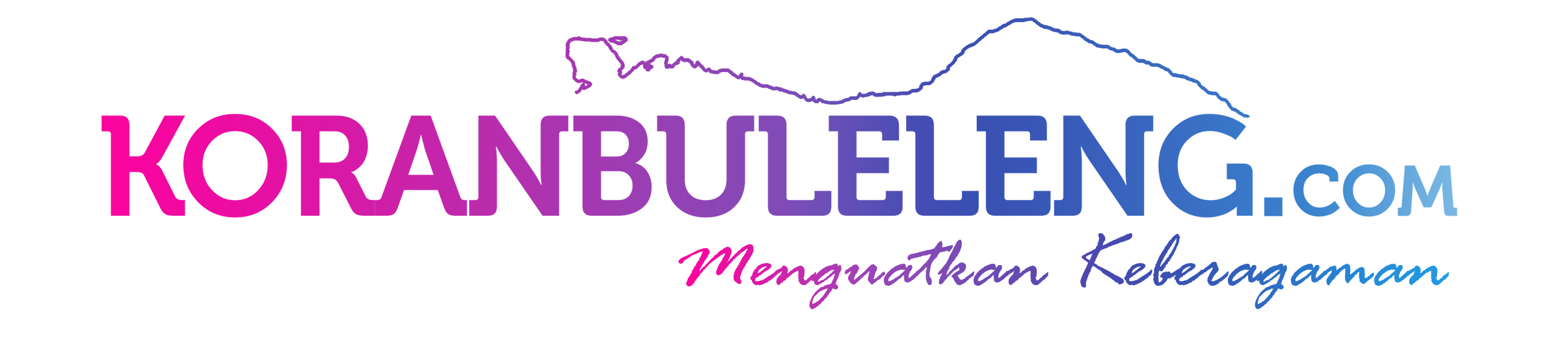Wayan Artika dengan Buku I Gusti Made Deblog, Master Seni Lukis Naturalis dalam Medan Seni Rupa Denpasar-Bali, dari I Kadek Wiradinata |FOTO : arsip pribadi|
Perdesaan di kaki Gunung Batukaru, dalam hal ini Kecamatan Pupuan, adalah pertanian (kopi, padi, buah-buahan). Kesenian kurang berkembang. Jika pun ada, sebatas memenuhi fungsi-fungsi sosial (angklung, jogged bumbung).

Seni wali wajib di setiap desa, berfungsi suci dalam odalan atau saba. Seni sanghyang (di Batungsel, misalnya) muncul secara tiba-tiba, lalu hilang. Sanghyang jaran disaksikan tahun 1970-an dan setelah tiga hari pementasan pun lenyap. Disusul munculnya sanghyang dedari hampir empat setengah dekade kemudian.
Seni wali (tari dan musik) di desa ini tidak pernah dipelajari. Selalu ada sekelompok masyarakat yang mengingat dengan baik. Ketika terjadi odalan besar, hanya beberapa hari ada waktu untuk menyiapkan suatu pertunjukan persembahan suci.
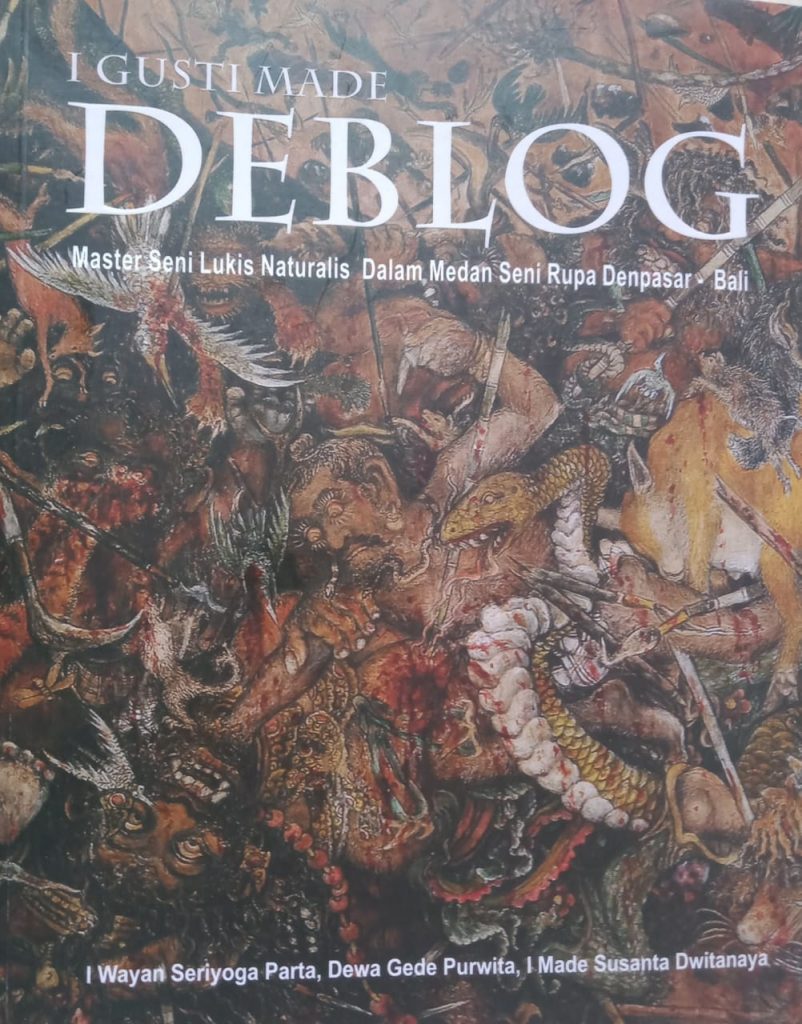
Saking suci dan terhormatnya, tabuh dan tarian ini hanya bisa dipelajari (dalam waktu sangat singkat) di areal pura. Ketika “pentas” mampu menarik perhatian seluruh karma. Para penari (daha, truna) menyerahkan tubuhnya kepada kekuatan suci untuk digerakkan.
Lantas, bagaimana anak-anak berkenalan dengan seni?

Mereka hanya sempat menikmati musik suci hampir sehari semalam ketika odalan. Pada upacara daur hidup selalu bisa menikmati musik angklung, jogged bumbung, dan wayang kulit parwa. Yang paling istimewa adalah wayang kulit. Pertunjukan ini paling dinantikan. Di bawah panggungan setinggi 1,5 meter, bertiang punyan buah (pinang); mereka berkenalan dengan cerita dan filsafat India lewat repertoar epik Mahabharata, dari pertunjukan seorang dalang asal Desa Tunjuk (Tabanan).
Tidak ada sanggar-sanggar di desa ini. Pelajaran seni yang sangat minim masuk lewat pendidikan SD. Lingkungan desa dan arsitektur pura atau rumah-rumah tidak memiliki elemen-elemen seni. Pura tanpa patung dewa atau mahluk-mahluk mitologis seperti naga, garuda, singa, atau sosok rangda. Gerbang dan tembok tiada ornament Bali. Kayu-kayu bangunan di pura juga tidak ada yang berukir. Parba juga tidak pernah berisi lukisan wayang kaca.
Satu-satunya seni patung ditemukan di Pura Panti, sepasang singa bersayap pada sendi. Pada suatu hari, mungkin di pertengahan dekade 1970-an, saya bertemu dengan gambar (istilah untuk lukisan) yang sungguh memukau. Ukurannya sangat besar.
Saya sangat kagum lukisan yang tidak saya pahami ini, di dinding rumah Pak Kilek, di Bangsing. Dominan warna biru dan beberapa ekor kuda yang gagah dikendalikan oleh seseorang laki-laki yang juga tidak kalah gagahnya. Kelak baru tahu itu lukisan uderan yang paling terkenal dalam Mahabharata, ketika Arjuna menerima nasihat dari Krisna, lahirnya Bhagawad Gita, di awal perang Saudara padang Kurusetra; untuk membangkitkan semangat berperang karena Pandawa ada di pihak darma. Maka tokoh utama lukisan ini adalah Krisna dan Arjuna.
Kekaguman berikutnya terhadap seni lukis ketika pertama kali lewat di gedung bioskop Tabanan Teater. Saya melihat dengan perasaan yang membara bentangan kain sangat lebar, menggambarkan adegan perang.
Di sekolah menengah pertama (SLUB 2 Saraswati Tabanan) amat menyukai pelajaran menggambar dari Pak Dewa Muliana. Lalu di SMA dari Pak Wayan Kawi. Tidak hanya menggambar untuk memenuhi tugas mata pelajaran. Saya memiliki banyak karya. Hal ini juga berlanjut sampai ke universitas.
Saya iri melihat rekan-rekan mahasiswa seni rupa yang kuliah “nyata”. Mereka mengerjakan satu tugas dan hasilnya jelas: patung, lukisan, foto, sketsa, keramik, anyaman, dll. Tapi saya tidak.
Ketika mendaki Batur di hari libur Idul Fitri, sempat mengunjungi Toya Bungkah, perpustakaan STA. Di sini ketemu buku tentang seniman Affandi. Karya-karya dalam buku ini memantik semangat saya “melukis” dan banyak bergaul dengan teman-teman di seni rupa.
Saya sangat suka menikmati seni. Untuk seni rupa saya terbiasa mengunjungi ruang pameran (terutama ketiak kuliah S2 di UGM). Banyak katalog dikumpulkan dan pernah menyaksikan langsung “Trilogi Celeng” seniman Lekra, Djoko Pekik (“Susu Raja Celeng”, “Berburu Celeng”, “Tanpa Bunga dan Telegram Duka”).
Setelah kembali ke Singaraja saya hanya sesekali mengunjungi museum karena jaraknya jauh dan lebih sering menonton pameran karya tugas mahasiswa seni rupa di kampus. Praktis intensitasnya menurun.
Di dalam kondisi itulah, tiba-tiba saya mendapat buku lukisan yang pasti sangat mahal, I Gusti Made Deblog, Master Seni Lukis Naturalis dalam Medan Seni Rupa Denpasar-Bali. Buku ini sampai ke pos satpam kampus lewat sahabat FB, I Kadek Wiradinata.
Tulisan ini sama sekali bukan ulasan mengenai buku tersebut tetapi ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada Komunitas Gurat Institute dan tentu saja para penulis yang telah menerbitkan buku yang sangat penting.
Tulisan ini juga sebagai bukti bahwa saya telah menerima buku tersebut dan saya sudah membaca dengan cermat, sebagai imbang terima yang paling mampu saya beri kepada Komunitas Gurat Institute serta ketiga penulisnya: I Wayan Seriyoga Parta, Dewa Gede Purmita, dan I ade Susanta Dwitanaya. (*)
Penulis : Dr. I Wayan Artika, S.Pd., M.Hum. (Dosen Undiksha, Pegiat Gerakan Literasi Akar Rumput pada Komunitas Desa Belajar Bali)